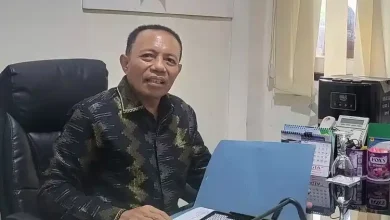Pemilu 2024 : Momentum Pendidikan Antikorupsi

Oleh : Imaduddin
Mahasiswa Magister Analisis Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Indonesia
“Korupsi yang semakin menggila”. Kiranya ungkapan tersebut tepat menggambarkan kondisi kekinian Indonesia. Tidak saja di level elit, namun juga merambah semakin luas, sampai di level pemerintahan yang paling rendah. Bagai virus, menjangkiti hampir semua sektor pelayanan publik. Tak ayal, berbicara korupsi membutuhkan kesabaran yang handal. Semenjak Indonesia merdeka, korupsi telah membayangi perjalanan negeri. Kalau waktu itu korupsi masih dilakukan dalam ruang terbatas yang hanya mampu dilakoni segelintir elit, kini bergerak cepat, massif tak terkendali. Tindakan “pencurian” uang negara marak dimana-mana, dari sentral Jakarta sampai pelosok terpencil. Banyaknya mantan pejabat yang menghuni “hotel prodeo” setidaknya memberi warna baru dalam signifikansi skandal. Penangkapan koruptor bagai agenda rutin yang entah kapan berakhirnya.
Gagalnya Pendekatan
Momentum reformasi sempat memberi harapan akan imaji pemberantasan korupsi. Belajar dari sejarah, asumsi tiadanya mekanisme check and balances dalam pemerintahan Soeharto menjadi alasan kronisnya korupsi mendera pertiwi. Dengan gegap gempita, check and balances menjadi prinsip utama dalam manajemen pemerintahan. Tiada satu lembaga pun yang tidak diawasi oleh lembaga lainnya. Tentunya dengan penegasan yang diinstitusionalisasi, konsepsi tersebut diadopsi sampai hari ini.
Dalam perjalanannya, KPK yang lahir sebagai kreasi baru dari prinsip check and balances memang menunjukkan agresivitas yang menakjubkan. Belum pernah ada lembaga yang begitu cekatan mengungkap borok korupsi, sampai memenjarakan pejabat negara. Sehingga apresiasi menjadi layak untuk diberikan. Namun yang menarik, seiring dengan “keberhasilan” KPK menjerat koruptor, seiring itu pula korupsi menjamur. Seakan tiada habis, pesimisme perlahan muncul di benak publik. Indeks prestasi korupsi Indonesia tidak pernah beranjak signifikan, bahkan masih dikategorikan sebagai negeri yang korup.
Selain itu, prinsip check and balances yang menjadi azimat justru kehilangan kesaktiannya. DPR yang salah satu fungsinya sebagai lembaga pengawas malah menjadi salah satu lembaga yang paling disorot. Walau oknum anggota yang melakukan, setidaknya menunjukkan lemahnya komitmen yang melekat pada institusi. Pun begitu dengan kekuasaan kehakiman, skandal yang menimpa “sang pemutus keadilan” terjadi berulang kali. Tak berhenti disitu, eksekutif pun tak terkecuali. Fenomena ini memang menyiratkan segudang tanya, mengingat ketiganya saling mengawasi dan berkedudukan sejajar.
Dalam analisisnya, Robert Kitgard (Membasmi Korupsi, 1998:3) menyatakan bahwa korupsi mempunyai segi-segi menguntungkan bagi yang berkuasa, bukan saja sebagai sarana untuk menggembungkan kantong tetapi juga sebagai mekanisme bagi penyelesaian politik, membina jalinan relasi, dan bahkan partisipasi politik. Persis dalam konteks hari ini, pendekatan legal kelembagaan memiliki cacat bawaan yang tak mungkin dinistakan. kecurigaan akan tatanan struktural yang ada memang sesuatu yang berdasar, karena kepentingan dan motif ekonomi politik berlindung dibaliknya. Konsekuensinya, tatanan struktural yang dibangun berbasis kerapuhan komitmen. Dan hal tersebut tentunya kontraproduktif dengan wacana dan imaji pemberantasan korupsi yang didengungkan. Anehnya, entah disadari atau tidak, realitas demikian terjadi tanpa ada koreksi konstruktif.
Kegagalan pendekatan ini tentunya semakin telanjang dengan tegasnya serangan balik koruptor. Dengan kelemahan internal struktural yang telah nyata, keampuhan serangan eksternal bukanlah sekadar ilusi. Niscaya fakta kriminalisasi, rekliminalisasi, sampai wacana “pembonsaian” kewenangan dan anggaran KPK membuktikannya. Sehingga tidak salah ketika pesimisme akan pendekatan legal kelembagaan diamini oleh John T. Nooman dalam argumentasinya, “korupsi itu pada intinya merupakan masalah etika dan seperti itulah sepanjang sejarah yang terlihat” (Bribes, 1984).
Momentum Pemilu 2024
Penulis melihat, praksisme pemberantasan korupsi yang menegasikan peran pembangunan karakter (character building) merupakan sebentuk kebijakan yang timpang dan tidak tuntas. Dikatakan timpang karena motif ekonomi politik pelaku korupsi tidak berhenti otomatis. Akibatnya, celah hukum akan terus dicari, bahkan hukum hanya dijadikan konsensus tak bergigi. Yang lebih parah, hukum justru akan dijadikan instrumen legitimasi, agung dalam rumusan namun menyimpan sekian kelemahan yang disengaja. Masyarakat awam tentu tidak mungkin mengerti akan hal tersebut karena wacana dan informasi bertumpu pada kelas elit.
Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi melalui pendidikan karakter merupakan sesuatu yang niscaya untuk dilakukan. Suatu proses yang terus-menerus, suatu “commencemet” yang selalu “mulai dan mulai lagi”, maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sebati (Paulo Freire, 1999). Sehingga penulis mengajukan dua kerangka pikir. Pertama, revitalisasi nilai-nilai kebudayaan anti-korupsi. Klasifikasi nilai tentunya mutlak untuk dilakukan, mengingat kesadaran anti-korupsi tidak jatuh begitu saja dari langit. Niscaya harus dikreasi dengan bersumber dari nilai-nilai positif kebudayaan. Tatkala klasifikasi telah selesai dilakukan, formalisasi nilai menjadi langkah lanjutan yang wajib. Tidak juga berhenti hanya disitu, sosialisasi dan indoktrinasi nilai harus disegerakan praksismenya.
Dalam konteks demikian, penyadaran tindakan koruptif tidak hanya dilakukan pada tahap penegakan. Namun, upaya sosialisasi sebagai bentuk pencegahan harus dilakukan. Perhelatan pemilu 2024 yang akan datang harus dijadikan momentum semangat pencegahan tindakan korupsi. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu wajib mengharuskan partai politik untuk melakukan kampanye antikorupsi. Setidaknya nilai-nilai antikorupsi ini terus digaungkan dalam pemilu. Kampanye nilai-nilai ini akan relevan kalau kita menggandeng partai politik, terlebih institusi demokrasi itu punya infrastruktur organisasi yang mapan. Hubungan mutualistik antara parpol dan publik akan terjalin, sebagai bagian dari pendewasaan kehidupan demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai antikorupsi. Lagi pula, partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang “semestinya” bagi kadernya serta masyarakat secara umum, sebagaimana bunyi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 “Partai politik antara lain berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas”. Kader-kader partai politik dapat mengadakan kampanye sekaligus mensosialisasikan pendidikan antikorupsi dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung. Saat yang sama, para wakil rakyat dari partai-partai menyerap aspirasi masyarakat, lalu mengartikulasikan agenda hajat hidup orang banyak sebagai bagian dari implementasi nilai antikorupsi di lapangan politik.
Dan kedua, mengefektifkan peran sekolah dan lembaga pendidikan sebagai garda terdepan indoktrinasi nilai. Harapannya, para perumus kebijakan yang terpilih dalam pemilu 2024 harus memprioritaskan internalisasi nilai anikorupsi dilembaga pendidikan. Ini berarti, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari kurikulum dan mendapat kedudukan sama dengan disiplin ilmu lainnya. Penegasan akan sifat permanen pendidikan antikorupsi perlu ditegaskan dalam aturan legal. Sehingga ketika terjadi pergantian rezim, perubahan kurikulum, pendidikan antikorupsi tetap menjadi mata ajar yang wajib adanya. Yang juga tidak boleh dilupakan, masyarakat harus terlibat penuh dalam proyek besar ini.
Akhirnya seperti yang diungkap Paulo Freire, harusnya sistem pendidikan menjadi kekuatan penyadar, maka manusia manusia yang sadar akan muncul dan bangkit secara kolektif. Generasi Indonesia yang nihil aksi koruptif bukan lagi sekadar mimpi.