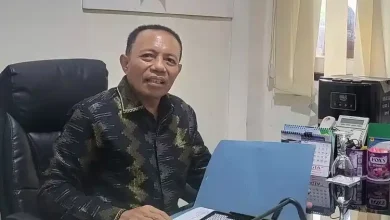Oleh: Farid Tolomundu – Pemerhati Kebijakan Publik dan Sekretaris Partai Gelora NTB
Indonesia sedang menghadapi paradoks kesehatan yang mematikan. Di satu sisi, pemerintah gencar mempromosikan transformasi kesehatan dan pembangunan rumah sakit megah di berbagai daerah. Namun di sisi lain, fondasi utama dari sistem tersebut—yakni ketersediaan dokter spesialis—sedang keropos akibat sistem rekrutmen mahasiswa kedokteran yang kian mirip dengan pelelangan barang mewah daripada seleksi intelektual.
Bobroknya sistem penerimaan mahasiswa kedokteran, terutama melalui jalur mandiri, telah menciptakan tembok api (firewall) yang memisahkan bakat terbaik dari peluang pengabdian. Biaya yang selangit bukan lagi sekadar angka untuk menutupi operasional laboratorium, melainkan manifestasi dari komersialisasi pendidikan yang menggadaikan masa depan kesehatan rakyat demi pundi-pundi institusi.
Komersialisasi di Gerbang Masuk
Jika kita menengok data penerimaan jalur mandiri di berbagai Perguruan Tinggi Negeri terkemuka untuk tahun akademik 2025/2026, angkanya sangat mengejutkan. Selain Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menyentuh puluhan juta rupiah per semester, calon mahasiswa seringkali dibebankan dengan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal yang bervariasi antara Rp200 juta hingga lebih dari Rp500 juta. Secara sistematis, negara seolah-olah memberikan restu bagi kampus untuk menjual “kursi” kepada mereka yang paling mampu membayar, bukan mereka yang paling kompeten atau memiliki jiwa pengabdian tinggi.
Ketika pendidikan kedokteran menjadi barang mewah, maka input yang dihasilkan pun terdistorsi. Kita tidak lagi memilih calon dokter berdasarkan ketajaman klinis atau empati, melainkan berdasarkan kapasitas saldo bank orang tua mereka.
Dampaknya sangat nyata: anak-anak cerdas dari pelosok daerah atau keluarga ekonomi lemah harus mengubur mimpi mereka. Padahal, justru mereka inilah yang biasanya memiliki keterikatan emosional dan keinginan lebih besar untuk kembali dan membangun daerah asal mereka.
Rantai Setan: Biaya Mahal dan Krisis Spesialis
Hubungan antara mahalnya biaya pendidikan dokter umum dengan krisis dokter spesialis di rumah sakit bukanlah kebetulan. Ini adalah hubungan sebab-akibat yang linear.
Seorang mahasiswa yang telah menghabiskan miliaran rupiah (akumulasi biaya kuliah, buku, hingga biaya hidup selama minimal 6-7 tahun) untuk menjadi dokter umum, secara psikologis dan finansial akan merasa tertekan untuk segera melakukan “pengembalian investasi” (return on investment). Hal ini mendorong mereka untuk terjun ke praktik-praktik yang paling menguntungkan secara ekonomi, yang biasanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Masalah semakin meruncing saat mereka ingin mengambil Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Hingga baru-baru ini, Indonesia menerapkan sistem yang sangat unik sekaligus aneh di dunia: calon dokter spesialis harus berhenti bekerja, membayar biaya pendidikan yang mahal, dan seringkali bekerja tanpa gaji di rumah sakit pendidikan selama bertahun-tahun.
Siapa yang mampu bertahan dalam sistem seperti ini? Hanya mereka yang memiliki modal besar. Akibatnya, jumlah produksi dokter spesialis kita sangat minim—hanya sekitar 2.700 per tahun, sementara kita membutuhkan setidaknya 29.000 hingga 30.000 dokter spesialis tambahan untuk mencapai rasio ideal.
Dampak di Bangsal Rumah Sakit
Krisis ini berujung pada antrean panjang di rumah sakit-rumah sakit daerah. Pasien kanker harus menunggu berbulan-bulan untuk kemoterapi karena kekurangan onkolog; anak-anak di daerah terpencil meninggal karena tidak ada dokter spesialis anak atau anastesi saat dibutuhkan operasi darurat.
Komersialisasi pendidikan telah menciptakan kasta dalam profesi medis. Dokter-dokter yang lahir dari sistem “bayar mahal” ini cenderung enggan ditempatkan di daerah terpencil. Bagi mereka, bekerja di RSUD di pelosok bukan hanya tidak menarik secara finansial, tetapi juga tidak mampu menutup utang atau modal yang telah dikeluarkan selama pendidikan. Akhirnya, distribusi dokter spesialis menumpuk di Jawa dan kota-kota besar, sementara rakyat di luar itu hanya bisa pasrah pada nasib.
Menuju Solusi: Memutus Rantai Pelelangan Kursi
Pemerintah, melalui UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, memang telah mencoba melakukan terobosan dengan sistem hospital-based (pendidikan spesialis berbasis rumah sakit) dan upaya menggratiskan biaya pendidikan. Namun, reformasi ini akan sia-sia jika “hulu”-nya, yaitu penerimaan mahasiswa kedokteran tingkat sarjana, masih dibiarkan menjadi ajang komersialisasi.
Beberapa langkah radikal perlu diambil:
- Penghapusan Uang Pangkal Jalur Mandiri: Negara harus mensubsidi penuh operasional Fakultas Kedokteran agar kampus tidak perlu “berjualan” kursi. Seleksi harus dikembalikan pada standar akademik dan tes psikologi pengabdian;
- Beasiswa Ikatan Dinas Masif: Calon mahasiswa dari daerah tertinggal harus diberikan akses gratis total dengan kontrak kerja ketat untuk kembali ke daerahnya sebagai dokter spesialis;
- Transparansi Biaya: Audit menyeluruh terhadap penggunaan dana IPI di universitas untuk memastikan tidak ada pemborosan atau penyimpangan.
Penutup
Kesehatan adalah hak asasi, bukan komoditas. Selama sistem penerimaan mahasiswa kedokteran kita masih memuja kekuatan uang, selama itu pula krisis dokter spesialis di rumah sakit tidak akan pernah usai. Kita sedang mempertaruhkan nyawa jutaan rakyat hanya demi mempertahankan sistem pendidikan yang elitis dan komersial.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan fakultas kedokteran sebagai unit bisnis. Jika tidak, rumah sakit kita akan terus menjadi monumen megah yang kosong tanpa tenaga ahli, dan rakyat akan terus membayar harga mahal atas bobroknya sistem yang kita pelihara hari ini. (*)