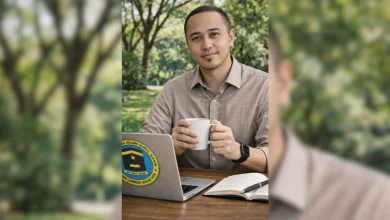Oleh: Irwan Julkarnain, SM. – Mahasiswa Magister Ekonomi Universitas Mataram
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, publik kembali bertanya tentang arah kebijakan pembangunan Nusa Tengarar Barat lima tahun mendatang. Situasi publik seperti ini hadir bukan tanpa alasan. Sebab, tinggal menghitung hari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda menggenapi 100 hari kerja-nya, tetapi kondisi NTB masih jalan di tempat dan bahkan belum ada kebijkan yang benar-benar bisa dirasakan dampakanya oleh masyarakat. Jusrtu ada kondisi yang amat rentan dalam lenskap ekonomi kita.
Dimana menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi dua kali lipat: minus 1,47 persen secara tahunan (y-on-y) dan juga minus 2,32 persen secara kuartalan (q-to-q) pada Triwulan I 2025. Pada kuartal I ini, kontraksi pertumbuhan ekonomi NTB sebagian besar akibat mandeknya ekspor tambang. Sektor ini biasanya menyumbang lebih dari 20 persen terhadap ekonomi NTB, tapi pada awal 2025 ekspornya nihil. Data tersebut setidaknya memberikan gambaran, bahwa ekonomi tanah Bumi Gora ini berada di titik rentan dan rawan. Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) dilakukan beberapa hari yang lalu, Tetapi ini hanya bersifat pada sektor tersier (Jasa dan Pariwisata). Tidak bisa menjawab persoalan kelesuan ekonomi sekarang. Mengingat eknomi lokal NTB juga banyak bertumpu pada pertanian, perikanan, dan UMKM. Sehingga mengandalkan event ini saja tidak cukup tanpa memperkuat fondasi ekonomi dasar justru ini akan memperlebar ketimpangan.
Visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda, “NTB Makmur Mendunia”, mengusung harapan agar Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat menjadi provinsi yang sejahtera dan berdaya saing global di masa yang akan datang. Namun, di balik ambisi besar ini, terdapat sejumlah tantangan nyata yang perlu dihadapi agar visi tersebut dapat terwujud. Salah satu yang paling mendasar adalah ketimpangan ekonomi, yang terus menghambat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah NTB perlu menyentuh akar masalah yang mendalam, bukan sekadar mengatasi gejala sementara. Tanpa keberanian untuk menyentuh akar permasalahan, maka pembangunan itu hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang kehilangan arah dan substansi.
Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Kita: Realitas yang Tak Terelakkan
Seperti yang kita ketahaui, pada tahun 2024, Gini Ratio NTB tercatat 0,364, sebuah indikator ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Meskipun terlihat penurunan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir, angka ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi masih menjadi masalah besar di NTB. Ketimpangan ini sangat terasa antara kota dan desa, serta antara daerah Lombok dan Sumbawa.
Di sisi lain, Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di NTB pada Maret 2024 tercatat sebesar 12,91%. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya sekitar 9%. Di mana data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu mendorong perbaikan signifikan bagi kelompok rentan dan tertinggal.
Ketimpangan ekonomi yang ada di NTB, sebagaimana disoroti oleh para ahli, merupakan cerminan dari struktur ekonomi yang tidak merata. Karl Marx dalam teori “Struktur Sosial dan Ketimpangan Kelas”-nya menekankan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi adalah hasil dari struktur sosial yang membagi kekuasaan dan sumber daya secara tidak adil. Di NTB, ketimpangan ini tercermin dalam ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, terutama pertambangan dan pariwisata, yang tidak mampu merata ke seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan mobilitas sosial.
Ketergantungan Sumber Daya Alam: Bisa Mengancam Keberlanjutan?
Provinsi NTB sangat bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam, terutama tambang tembaga dan emas di Batu Hijau, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini. Meskipun sektor ini menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketergantungan pada tambang membawa dampak negatif yang besar.
Dutch Disease, sebuah teori yang diperkenalkan oleh Corden dan Neary (1982), menjelaskan bagaimana kelebihan pendapatan yang diperoleh dari sektor ekstraktif dapat merusak sektor lain yang lebih produktif, seperti pertanian atau manufaktur. Ini yang terjadi di NTB, di mana sektor-sektor selain pertambangan, seperti pertanian dan industri pengolahan, menjadi terabaikan. Padahal, sektor-sektor inilah yang lebih padat karya dan memiliki daya sebar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat lokal.
Selain itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, seperti acaman deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, semakin menambah tantangan yang dihadapi oleh NTB. The Tragedy of the Commons, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Garrett Hardin (1968), juga relevan di sini, dimana ketika sumber daya alam dikelola tanpa memperhatikan keberlanjutannya, maka kerugian ekologis dan sosial akan dialami oleh seluruh masyarakat dalam jangka panjang. NTB membutuhkan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan konservasi lingkungan agar tidak terjebak dalam pembangunan yang menghancurkan daya dukung ekologisnya sendiri.
Pembangunan yang Terpusat dan Kurangnya Inklusi
Pembangunan di NTB, terutama di Pulau Lombok, tampaknya masih terfokus pada proyek-proyek besar seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika dan pariwisata berkelas internasional. Meskipun sektor pariwisata memberi kontribusi besar terhadap perekonomian, distribusi manfaat ekonomi dari sektor ini masih sangat terbatas. Banyak masyarakat lokal yang tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi pariwisata, baik melalui lapangan pekerjaan berkualitas maupun keikutsertaan dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas.
Ketimpangan ini memperbesar kesenjangan antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran, serta menciptakan ketidakadilan spasial yang kronis. Dalam perspektif teori “Development as Freedom” oleh Amartya Sen (1999), pembangunan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sebagai proses untuk memberikan kebebasan pada individu untuk mengakses peluang-peluang hidup yang lebih baik.
Dalam hal ini, pembangunan NTB harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya yang berada di kota besar, tetapi juga yang ada di daerah terpencil. Jika ini tidak terjadi, maka NTB hanya akan menjadi provinsi dengan “pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan”. Pemerataan bukan hanya soal distribusi pendapatan, tetapi juga soal distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya produktif.
Sebelum Mendunia, Kita Perlu Kebijakan yang Menyentuh Akar
Salah satu dari sepuluh program unggulan Iqbal-Dinda adalah memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan pendapatan perkapita masyarakat sebagai pondasi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Gagasan yang amat bagus, tetapi lagi-lagi kita belum melihat pondasi yang jelas dari gagasan ini. Oleh karena itu ada bebera hal yang penulis perlu sarankan, melalu pendekatan teori ekonomi dan realitas yang ada. Visi “NTB Makmur Mendunia”, membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata perlu diterapkan. Banyak cara yang bisa diambil, seperti;
1. Diversifikasi Ekonomi yang Berkelanjutan
Dalam konteks membangun ekonomi NTB yang makmur dan mendunia, upaya diversifikasi ekonomi menjadi sebuah keniscayaan strategis. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif seperti pertambangan tidak hanya berisiko secara ekologis, tetapi juga tidak memberikan efek ganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal. Data dari BPS menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB NTB memang tinggi sekitar 16%, dengan mineral utama emas. namun menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat minim. Sebaliknya, sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang justru menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti akses pasar, pembiayaan, dan teknologi.
Joseph Schumpeter, melalui konsep “Creative Destruction”, mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi sejati muncul dari keberanian untuk meninggalkan pola ekonomi lama yang stagnan demi memberi ruang bagi sektor-sektor baru yang lebih inovatif dan produktif. Dalam konteks NTB, ini berarti mendorong transformasi ekonomi dari ekstraktif ke sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian organik, perikanan berkelanjutan, energi terbarukan, serta industri kreatif berbasis kearifan lokal. Diversifikasi ini tidak hanya berdampak pada ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan global seperti fluktuasi harga komoditas atau krisis iklim tetapi juga memperkuat basis ekonomi lokal yang inklusif dan merata
2. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal
Salah satu warisan penting dari pemerintahan NTB sebelumnya yang layak untuk dilanjutkan dan ditingkatkan adalah agenda pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, hingga 2023 tercatat lebih dari 320.000 pelaku UMKM tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan dominasi usaha di sektor perdagangan, pengolahan makanan, kerajinan tangan, serta pertanian olahan. Namun, sebagian besar UMKM ini masih beroperasi secara informal, menghadapi keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar digital.
Michael Porter, dalam teorinya “Competitive Advantage of Nations”, menekankan bahwa daya saing suatu negara atau daerah tidak ditentukan semata oleh sumber daya alamnya, tetapi oleh kemampuan untuk menciptakan nilai tambah berbasis kekuatan lokal dalam hal ini UMKM yang terhubung dengan rantai pasok nasional maupun global. Artinya, pemberdayaan UMKM bukan sekadar program sosial-ekonomi, tetapi strategi untuk menumbuhkan basis ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi. Pemerintahan Iqbal-Dinda perlu memastikan bahwa penguatan UMKM menjadi bagian integral dan terukur dari kebijakan ekonomi makro dan sektoral. Ini mencakup penyediaan akses pendanaan inklusif, pelatihan berbasis kebutuhan riil pasar, serta integrasi UMKM dalam ekosistem digital dan logistik regional. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan membangun konektivitas pasar yang lebih luas, UMKM NTB dapat naik kelas menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Peningkatan Infrastruktur yang Merata
Pembangunan infrastruktur yang merata harus menjadi prioritas strategis pemerintahan Iqbal-Dinda. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi hambatan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Data BPS NTB tahun 2023 mencatat bahwa akses jalan layak di pedesaan baru mencapai sekitar 64%, sementara akses internet stabil dan air bersih di beberapa kabupaten seperti Dompu dan Bima masih tertinggal dibandingkan wilayah seperti Mataram atau Lombok Barat.
Jeffrey Sachs, dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif dan terjangkau adalah fondasi untuk pemerataan kesejahteraan. Infrastruktur bukan sekadar jalan dan jembatan, tetapi juga meliputi jaringan komunikasi digital, sanitasi, energi terbarukan, dan sarana pendidikan serta kesehatan yang memadai. Akses yang terbatas terhadap infrastruktur ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas masyarakat desa, sulitnya UMKM berkembang, serta kesenjangan kualitas hidup antardaerah.
Pemerintah NTB perlu mengadopsi pendekatan pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan lokal dan berorientasi pada konektivitas antarwilayah, sehingga desa-desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan akses jalan produksi pertanian, sinyal internet untuk desa wisata dan sentra UMKM, serta infrastruktur irigasi mikro di daerah tandus dapat menjadi bentuk intervensi strategis yang mengangkat potensi lokal sekaligus mempersempit kesenjangan wilayah.
4. Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Tantangan lain yang paling mendasar adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di NTB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada di angka 71,38, masih berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu komponennya, yakni rata-rata lama sekolah, hanya mencapai sekitar 8,5 tahun, yang berarti banyak warga NTB belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Program seperti Beasiswa NTB yang di garap oleh Pemerintahan Zul-Rohmi sangat bagus untuk Kembali diterapkan, sebab ini investasi jangka Panjang. Investasi dalam human capital sebagaimana ditegaskan oleh ekonom Gary Becker, merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Tanpa SDM yang terampil, berpendidikan, dan adaptif terhadap perubahan teknologi, NTB hanya akan menjadi ladang investasi pasif tanpa posisi tawar.
Dilain dari pada itu, Pemerintahan Iqbal-Dinda perlu memberi penekanan lebih pada pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global. Program pelatihan berbasis kejuruan, pendidikan kewirausahaan, hingga peningkatan literasi digital harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan SDM. Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan juga perlu diperkuat agar tercipta ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan. Impian NTB mendunia hanya akan berakhir pada ketergantungan jangka panjang terhadap investasi luar tanpa kemandirian ekonomi yang sejati. SDM bukan sekadar angka statistik, tapi penentu arah masa depan daerah.
5. Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam
NTB dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dari tambang tembaga dan emas, potensi perikanan, hingga hutan dan lahan produktif. Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Data BPS NTB 2023 menunjukkan bahwa kabupaten penghasil tambang seperti Sumbawa Barat justru masih mencatatkan angka kemiskinan di atas 13%, memperlihatkan adanya kesenjangan antara eksploitasi sumber daya dengan distribusi manfaatnya. Dalam konteks ini, urgensi reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA) menjadi sangat penting.
Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi, dalam teorinya tentang pengelolaan kolektif sumber daya bersama (common-pool resources), menekankan bahwa pengelolaan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas lokal dapat mencegah eksploitasi berlebih sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintahan Iqbal-Dinda perlu merombak pendekatan tata kelola SDA yang selama ini terlalu tersentralisasi dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Model tata kelola berbasis masyarakat, seperti hutan desa, tambang rakyat berizin, atau zona konservasi berbasis adat, bisa menjadi strategi alternatif yang tidak hanya menjaga keberlanjutan ekologis, tetapi juga menumbuhkan ekonomi lokal secara langsung.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam perizinan, redistribusi pendapatan dari sektor ekstraktif, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus menjadi norma baru dalam tata kelola daerah. Tanpa reformasi ini, NTB hanya akan menjadi penonton di tanahnya sendiri, sementara manfaat ekonominya mengalir ke luar.
Kita ingin Visi “NTB Makmur Mendunia” harus lebih dari sekadar retorika politik. Visi ini harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis pada keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan pemerataan pembangunan, dan paling penting jelas gagasan dan kerjanya. Kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah, seperti ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada sektor ekstraktif, hanya akan menciptakan ketimpangan yang lebih dalam.
Dengan mengimplementasikan teori-teori pembangunan yang inklusif, memperbaiki struktur sosial dan ekonomi, serta melakukan diversifikasi sumber daya ekonomi, NTB dapat bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing di kancah global. Namun, langkah ini memerlukan komitmen yang kuat, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat. Tanpa itu semua, NTB hanya akan berjalan di tempat dalam kemasan mimpi besar yang kosong substansi. (*)