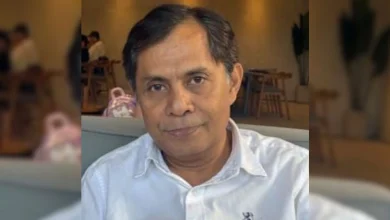Oleh: Salman Faris
Saya sangat beruntung dapat menonton dua pertunjukan teater yang cukup bagus secara ide. Pada tanggal 18 Oktober 2025, saya menyaksikan Hikayat Gajah Duduk yang dipentaskan oleh Teater Kamar Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2025, Bengkel Aktor Mataram mementaskan Dende Tamari, yang juga saya tonton secara penuh.
Dua kelompok teater ini merupakan salah satu kelompok teater penting dalam sejarah perkembangan kesenian di NTB. Dua karya yang dipentaskan pun, cukup mendorong daya tafsir atas ide-ide yang menunjukkan kemampuan reinvensi atas fenomena sosial dan budaya.
Hanya saja, sepanjang pertunjukan, saya sangat terganggu dengan keadaan gedung pertunjukan, yang saya sendiri tidak mempunyai banyak pilihan kata untuk menilai selain menyebut gedung pertunjukan yang usang dan terbelakang. Dari segi keperluan 1) pencapaian estetika, 2) keperluan kenyamanan serta 3) keselamatan, sungguh memang usang dan terbelakang. Karena kedua hal itu, maka dengan penuh keyakinan saya menegaskan bahwa sungguh malang Taman Budaya NTB.
Kondisi tersebut tentu saja tidak dapat menyumbang secara signifikan terhadap pencapaian artistik kelas tinggi. Jangankan bermain di tingkat global sebagaimana arah pengembangan NTB saat ini, bermain di wilayah lokal saja, Taman Budaya NTB masih kalah jauh.
Karena itu, talenta muda industri kreatif yang semestinya dapat berkembang jauh lebih pesat, terkendala oleh infrastuktur Taman Budaya NTB yang malang dan terbelakang. Jangankan talenta muda bermimpi untuk menciptakan inovasi dan invensi dalam dunia industri kreatif, sekadar untuk memenuhi keperluan kreatif yang paling sederhana pun, Taman Budaya NTB masih sangat jauh dari harapan. Bahkan, harapan itu tidak ada.
Taman Budaya NTB memikul mandat ganda yang esensial. Lembaga tersebut adalah benteng preservasi sekaligus inkubator inovasi. Rahim tempat tradisi diciptakan kembali melalui daya kembang sekaligus laboratorium tempat ekspresi artistik kontemporer diuji dan dikembangkan.
Namun, fungsi kedua ini, fungsi inovasi, secara fundamental terikat pada penguasaan medium. Fungsi Taman Budaya NTB sebagai ibu kandung inovasi kesenian dan kebudayaan secara mendasar bergantung pada adaptasi dan penguasaan teknologi. Dalam seni pertunjukan kontemporer, teknologi bukanlah sekadar hiasan. Lebih jauh dari itu, teknologi adalah infrastruktur, tata bahasa, dan medium ekspresi itu sendiri. Kegagalan mengadopsi dan menguasai teknologi pertunjukan yang relevan secara profesional adalah sebuah vonis mati bagi pencapaian artistik.
Inilah tragedi presisi yang melanda Taman Budaya NTB. Sejak berdirinya pada 23 April 1991, institusi ini terperangkap dalam stagnasi teknologi panggung yang akut. Mungkin saja pada awal berdirinya dulu, Taman Budaya NTB menjadi yang terdepan. Namun, itu adalah masa lalu.
Karena itu saya melihat Institusi ini pada masa kini dan masa depan yang jelas menunjukkan tidak sekadar tertinggal, tetapi secara fungsional terbelakang. Juga terisolasi dari dialog global.
Untuk mengukur kedalaman jurang keterbelakangan ini, kita dapat menggunakan dua tolok ukur penting yang merepresentasikan standar minimum dalam praktik pertunjukan teknis global yakni 1) substansi pemikiran dalam disiplin tata cahaya profesional dan 2) disiplin rekayasa mekanis panggung.
Kesenjangan antara apa yang dianggap fundamental dalam standar global dan apa yang dipraktikkan di Taman Budaya NTB adalah sebuah manifestasi kemalangan yang sistemik dan memalukan.
Mari kita bedah defisit ini pada pilar pertama, yaitu pencahayaan. Teks standar dalam tata cahaya mengartikulasikan bahwa pencahayaan modern adalah disiplin yang presisi mengenai kontrol. Ini bukan sekadar soal terang dan gelap. Ini adalah tentang kemampuan artistik untuk mengontrol kualitas warna melalui pencampuran aditif LED, bukan sekadar filter gel usang. Ini tentang mengontrol tekstur melalui proyeksi gobo (go between optics) dan pemfokusan optik yang tajam. Yang terpenting, ini tentang mengontrol waktu melalui sistem antrean adegan digital (cue digital) yang kompleks.
Standar profesional mengasumsikan sebuah ekosistem di mana konsol digital (papan kendali) berkomunikasi dengan peranti keras melalui protokol data yang stabil, memungkinkan transisi yang mulus dan sinkronisasi yang presisi.
Apa yang kita saksikan di Taman Budaya NTB? Sebuah pencahayaan yang bahkan tidak layak disebut pencahayaan pertunjukan. Kita tidak berbicara tentang ketiadaan lampu otomatis canggih, kita berbicara tentang ketiadaan pemahaman fundamental terhadap bahasa pencahayaan. Praktik di sana masih terkunci pada paradigma sekadar menyalakan lampu.
Konsep patching digital, pemrograman tumpukan adegan (cue stack), atau bahkan pemahaman dasar fotometrik untuk memilih instrumen yang tepat untuk jarak tembak tertentu adalah sebuah konsep yang sepenuhnya asing di Taman Budaya NTB.
Lebih parah lagi adalah pengabaian total terhadap aspek paling krusial yang menopang seluruh disiplin ini, yaitu keselamatan. Standar profesional minimum menuntut seorang teknisi mampu melakukan kalkulasi beban kelistrikan, berdasarkan Hukum Ohm (rumus dasar kelistrikan) dan perhitungan daya, untuk mencegah kelebihan beban sirkuit dan bahaya kebakaran. Standar profesional menuntut pemahaman absolut tentang pembumian (grounding) dan praktik kerja yang aman.
Di Taman Budaya NTB, jangankan diatur oleh metodologi diagnostik dan keselamatan, kelistrikan panggung lebih sering diatur oleh keberanian dan keberuntungan semata (modal nekad, pasrah, dan bongoh). Panggung Taman Budaya NTB, secara harfiah, adalah sebuah area berbahaya yang beroperasi atas dasar kelalaian yang terinstitusionalisasi.
Jika defisit bahasa cahaya sudah sedemikian parah, kondisi pilar kedua, rekayasa panggung, lebih menyedihkan. Panduan utama mengenai rekayasa panggung adalah sebuah manual tentang fisika terapan. Inti dari disiplin ini adalah transformasi pergerakan panggung dari sekadar tenaga kerja manual menjadi sebuah sistem mekanis yang terkalkulasi, aman, dan dapat diulang. Disiplin ini dibangun di atas fondasi kalkulasi gaya, torsi, dan daya.
Disiplin ini menuntut seorang desainer teknis untuk menghitung gaya inersia dan gesekan untuk menggerakkan sebuah gerobak panggung (wagon), atau menghitung momen inersia dan torsi yang dibutuhkan untuk sebuah panggung putar (turntable).
Di Taman Budaya NTB, desain mekanis adalah sebuah konsep yang sepenuhnya kosong. Pergerakan skenografi tidak diatur oleh aktuator hidraulik, pneumatik, atau bahkan motor listrik sederhana yang terhubung ke katrol (winch) atau derek. Pergerakan tersebut diatur oleh tenaga otot para pekerja panggung dalam kegelapan.
Ini bukan otomatisasi panggung (otomatia skenik), ini adalah praktik gotong royong era prateknologi yang tidak memiliki presisi, tidak dapat diulang, dan sangat tidak efisien. Sekaligus sangat primitif.
Aspek sentral dari rekayasa panggung profesional adalah kalkulasi faktor keamanan. Seorang teknisi profesional menghitung beban kerja aman dari seutas kabel baja atau kapasitas sebuah motor, seorang teknisi profesional merancang sistem gagal-aman (fail-safe) dan rem darurat.
Di Taman Budaya NTB, faktor keamanan digantikan oleh doa. Ketidakmampuan untuk mengadopsi prinsip rekayasa dasar ini berarti membiasakan (bahkan membudaya) pekerja kreatif yang pentas di Taman Budaya NTB secara efektif terbatas pada skenografi statis. Setiap ambisi untuk menciptakan panggung yang dinamis, bergerak, atau bertransformasi secara mekanis, sebuah standar dalam pertunjukan kesenian dan kebudayaan kontemporer, seketika dipadamkan oleh keterbelakangan infrastruktur ini.
Karena itu, saya ingin menegaskan bahwa keterbelakangan teknologi yang memalukan ini bukanlah takdir. Ini jelas merupakan produk dari tiga kegagalan struktural yang saling mengunci.
1) Lemahnya kebijakan penganggaran. Ini adalah kegagalan cara pandang (epistemologis) di tingkat pengambil kebijakan. Anggaran yang dialokasikan merefleksikan pandangan para pengambil kebijakan anggaran bahwa seni adalah aktivitas seremonial berbiaya rendah, bukan sebuah industri profesional berteknologi tinggi. Mereka berpikir bahwa kebudayaan adalah santapan makhluk halus. Investasi pada konsol pencahayaan digital (papan kendali lampu) atau sistem katrol (winch) bermotor dianggap sebagai kemewahan yang boros, bukan sebagai infrastruktur dasar yang esensial, setara dengan membeli mikroskop untuk laboratorium biologi. Mereka beranggapan bahwa untuk menjadi tuan di rumah sendiri dalam arus deras global dan industri, tidak perlu berinvestasi pada kebudayaan. Bahkan bisa jadi, di kepala mereka tak pernah samasekali terlintas tentang kesenian dan kebudayaan.
2) Rendahnya pengetahuan pemangku kebijakan. Baik di legislatif maupun eksekutif, terdapat defisit literasi teknis yang akut. Mereka tidak memiliki kerangka konseptual untuk memahami urgensi pengembangan teknologi kesenian. Mereka juga buta huruf dalam menerima pentingnya teknologi dalam pemajuan kebudayaan. Sudah pasti, mereka tidak dapat membedakan antara lampu sebagai alat penerangan dan instrumen pencahayaan sebagai alat artistik presisi. Mereka tidak memahami bahwa kalkulasi beban kelistrikan dan rekayasa mekanis adalah prasyarat keselamatan yang tidak dapat ditawar, bukan sekadar keperluan praktis yang tidak perlu.
3) Miskinnya Sumber Daya Manusia (SDM). Ini adalah jantung dari kemalangan. Bahkan jika kita secara ajaib menghibahkan peralatan canggih hari ini, siapa yang akan mengoperasikannya? Siapa yang memiliki kompetensi kognitif untuk melakukan pencarian dan perbaikan masalah (troubleshooting) alur sinyal DMX, atau menghitung rasio gearbox yang tepat untuk sebuah motor yang menggerakan teknologi panggung? Standar profesional menuntut seorang praktisi yang bekerja dengan pengetahuan mendalam (kognitif), seorang insinyur-arsitek sekaligus seniman yang mampu berpikir, menghitung, dan mendiagnosis. Taman Budaya NTB gagal total menciptakan kader ini sehingga terjebak dalam lingkaran setan yakni teknologi primitif menarik SDM berkualitas rendah, yang kemudian membenarkan ketiadaan anggaran untuk teknologi baru.
Taman Budaya NTB, dalam kondisinya saat ini, adalah sebuah anomali yang gagal. Institusi ini gagal sebagai laboratorium inovasi pekerja kreatif, gagal sebagai fasilitator profesionalisme talenta muda kreatif NTB, dan gagal sebagai pelindung keselamatan bagi pekerja kreatif yang dinaunginya. Institusi ini hanya berfungsi sebagai monumen hidup bagi stagnasi birokrasi dan kemiskinan intelektual.
Karena itu, saya kembali pada kesimpulan yang sama dengan yang telah saya sampaikan puluhan tahun yang lalu (baca tulisan saya yang berjudul Taman Budaya NTB: Bubarkan Saja, yang diterbitkan Lombok Pos pada tahun 2013). Daripada membiarkan institusi ini terus-menerus bergerak dalam kemalangan dan keterbelakangan, dan tak henti-henti memberikan ilusi kemajuan kesenian dan kebudayaan yang memabukkan, Taman Budaya NTB lebih baik dibubarkan.
Keberadaannya dalam kondisi teknologi yang primitif dan tanpa harapan ini lebih merupakan penghinaan terhadap marwah kesenian dan harkat kebudayaan itu sendiri.
Malaysia, 7 November 2025
Catatan: Baca buku: Stage Lighting: The Technicians’ Guide yang ditulis oleh Skip Mort dan Mechanical Design for the Stage oleh Alan Hendrickson. (*)