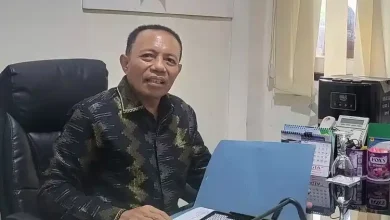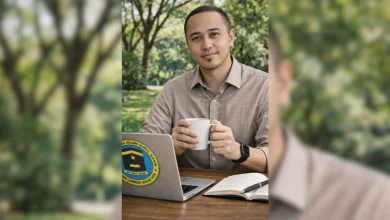Oleh: Dr. Alfisahrin, M.Si. – Dosen Universitas Bima Intersional-MFH dan Staf Everywhere Ahli di DPD RI
Mengawali tulisan ini saya ingin mengutip satu kalimat dari Filsuf kenamaan Prancis Jean Jacques Rousseau dalam Du Contrac Social (1762) Man Is Born Free, and He is In Chains. Artinya manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia berada dalam belenggu. Secara alami dan kodrati manusia memang bebas, namun, masyarakat dan sistem sosialah yang seringkali membatasi kebebasan manusia melalui sejumlah norma, hukum, dan struktur kekuasaan yang menindas. Manusia akan mencapai kebebasan sejatinya jika hidup dalam tatanan sosial yang adil, setara dan demokratis berdasarkan apa yang menjadi kehendak umum atau (volonte generale).
Chomsky dalam Manufacturing Consent (1988) juga menjelaskan bahwa kebebasan manusia bukan hanya hak politik, tetapi karena kodratnya manusia sebagai makhluk rasional dan moralis. Di Indonesia kebebasan bicara dan ekspresi seringkali dihadapkan pada arogansi, hegemoni bahkan tirani kekuasaan. Tidak sedikit orang dipenjara hanya karena menyampaikan pendapat berani dan kritis terhadap kebijakan negara yang tidak pro rakyat dan merugikan kepentingan publik. Kritik masih dianggap sebagai perlawanan, bicara jujur dianggap kontra, mengucapkan pendapat berbeda dicap permusuhan. Ironisnya, kebebasan bicara dan berekspresi justru sering hilang di dunia kampus yang mimbar akademiknya dijamin oleh undang-undang. Raibnya kebebasan bicara dan ekspresi yang demokratis menyebabkan banyak aspirasi mahasiswa dan dosen yang tersumbat. Sehingga rapat-rapat di kampus pun jarang lagi ada dinamika akademik dan perdebatan sengit soal ide dan adu gagasan tentang persoalan fundamental akademik dan negara.
Forum rapat akademik pun seringkali berjalan datar layaknya orang berdoa, bukan berdiskusi mencari kebenaran ide dan pengetahuan logis untuk membangun kapasitas pelayanan dan kualitas institusi melainkan hanya formalitas. Saya pun jarang lagi menjumpai kelas-kelas pembelajaran akademis, di mana dosen dengan mahasiswa berdebat sengit bicara tentang wacana kritis dan filosofis, tentang kerusakan ekologi, banjir, kekerasan sosial, nepotisme, kolusi, dan instabilitas negara. Kelas-kelas akademik seolah hilang gairah dan cita rasa ilmu dan paradigma karena terkesan hanya gugurkan kewajiban mengajar dosen. Mana ada dosen dari ratusan perguruan tinggi yang berani menggugat soal ketimpangan akses politik, ekonomi, dan infrastruktur sosial yang lomboksentris di NTB.
Kampus sudah terlalu birokratis dan politis sehingga civitas akademik banyak yang kelihatannya sibuk urus administrasii akademik bukan tentang substansi akademik yakni menemukan kebenaran ilmiah, teori dan konsep-konsep akademik baru. Sehingga banyak karya-karya akademik kampus kerapkali hanya sebatas publikasi untuk gugurkan kewajiban dosen dan syarat kenaikan pangkat bukan referensi solutif bagi pemerintah dalam mengatasi masalah mendasar publik seperti kemiskinan ekstrim, ketimpangan ekonomi, layanan kesehatan buruk, krisis air bersih, dan akses pendidikan yang mahal. Ketidakadilan, kekerasan dan feodalisme justru banyak terjadi di kampus sebagai tempat yang harusnya steril dari praktek primordialitas. Ramai diberitakan di media jika kampus sering menjadi arena terselubung pelecahan seksual, bullying, plagiasi dan kekerasan verbal meminjam istilah Piere Bordieau. Bagi saya kampus sebagai benteng nilai, sumber kebenaran ilmiah dan pusat inovasi gagal memainkan peran sebagai produsen insan akademik humanis dan kritis.
Budaya berpikir kritis tidak diajarkan lagi di kampus-kampus sebagai instrumen untuk tetap menjaga pengetahuan, nalar logik dan kewarasan mahasiswa dan publik, filsafat sebagai metode berpikir radikal, kritis dan sistematis sudah raib tidak diajarkan lagi di banyak kampus. Akibatnya, nyaris tidak ada dialektika akademis yang ada hanya kompromi, akomodasi, dan normalisasi terhadap kapitalisme serta komersialisasi akademik. Kritik dengan premis akademis pun terhadap praktek kekuasaan kampus akan dicap tidak loyal, mahasiswa kritik dosen dicap tidak etis, mahasiswa kritik buruknya layanan akademik langsung dibungkam. Bukankah, kampus memang arena pertarungan gagasan dan melatih ketajaman berpikir. ratusan tahun yang lalu Filsuf Jerman Frederick Hegel dalam Critique of Pure Reason (1781) mengajarkan tentang pentingnya perselisihan ide dan antar ide -gagasan melalui tesis, antitesis dan sintesis untuk menghasilkan kualitas pemikiran ilmiah.
Kampus bukan sekadar tempat orang menimba ilmu, melainkan ruang pembentukan cara berpikir manusia yang merdeka. Di kampuslah nalar manusia diuji, diperhalus, dan diarahkan agar mampu membaca realitas dengan tajam. Fungsi sejati pendidikan tinggi bukanlah mencetak lulusan dengan nilai akademik tinggi, melainkan menumbuhkan pribadi yang berpikir kritis, berani mempertanyakan, dan bertanggung jawab terhadap gagasannya. Namun, ideal itu kian pudar di banyak kampus. Dalam praktiknya, pendidikan tinggi sering kali terjebak pada rutinitas administratif, perburuan nilai, dan orientasi pasar kerja. Ruang-ruang kuliah dipenuhi hafalan teori tanpa keberanian untuk menggugat. Akibatnya, kampus kehilangan perannya sebagai laboratorium nalar dan berubah menjadi pabrik gelar. Kampus seharusnya menjadi arena dialektika—tempat pertemuan gagasan yang berbeda dan kadang bertentangan. Di sanalah mahasiswa belajar menimbang argumen, menguji data, serta menemukan kebenaran melalui perdebatan yang sehat.
Nalar kritis lahir dari benturan gagasan, bukan dari kepatuhan buta terhadap satu sumber pengetahuan. Dosen memiliki peran vital dalam menumbuhkan atmosfer dan budaya intelektual yang kritis. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi penuntun nalar mahasiswa agar terus bertanya dan menggugat segala realitas. Dosen yang baik tidak memaksakan pandangannya, melainkan menantang mahasiswa untuk berpikir lebih jauh melalui duel argumen. Mahasiswa pun perlu berani mempertanyakan, bukan hanya mencatat dan menghafal. Karena berpikir kritis adalah hasil dari keberanian untuk meragukan, bukan dari kepastian yang diberikan.
Kampus sebagai Mesin Kepatuhan
Kampus, dalam tradisi intelektual modern, sejatinya adalah ruang suci bagi kebebasan berpikir. Ia adalah miniatur republik tempat gagasan diuji, perbedaan dihormati, dan kebenaran dicari melalui dialog rasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, atmosfer itu perlahan redup. Mengutip Steven Levitsi dalam How Democracy Dies (2018) bahwa demokrasi mati bukan karena kudeta militer dan revolusi tetapi karena kampus mati pelan-pelan bukan karena kudeta bersenjata, melainkan melalui proses legal yakni kepemimpinan yang otoriter yang perlahan melemahkan institusi dan norma demokrasi dari dalam lewat birokrasi yang dibuat kaku, kebijakan yang membuat apatisme, dan kooptasi kekuasaan pada ruang berpikir bebas civitas akademik. Demokrasi kampus yang dulu hidup dalam bentuk pemilihan mahasiswa yang serupa dengan pilkada dan pilpres, sekarang diganti oleh pimpinan perguruan tinggi dengan praktek aklamasi dan intervensi. Agar terpilih mahasiswa bermental beo yang hanya tau tunduk dan manggut. Sehingga mudah diatur dan leluasa dikendalikan supaya tidak mengritik manajemen buruk kampus. diskusi publik tidak boleh sering-sering digelar agar kesadaran kritis mahasiswa tidak tumbuh subur atau aksi solidaritas kini tergantikan oleh ritual administratif. Mahasiswa lebih sibuk mengurus sertifikat, organisasi kemahasiswaan berubah menjadi perpanjangan tangan birokrasi, sementara dosen yang kritis dibungkam oleh mekanisme penilaian kinerja yang ketat. Kampus yang seharusnya menjadi benteng kebebasan intelektual justru berubah menjadi pabrik gelar, dengan logika pasar dan kepatuhan sebagai mata uang utamanya.
Saya pikir salah satu tanda alarm matinya demokrasi kampus adalah ketika ia berhenti menjadi ruang dialog. Ada ratusan bahkan ribuan rektor dan dosen di Indonesia namun, berapa banyak yang berani bicara kritis terhadap ketidakadilan kekuasaan negara. Dosen siapa dan kampus mana yang lantang bicara dan bersuara atas alienasi oligarki dan praktek eksploitasi di perguruan tinggi. Dehumanisasi terjadi telanjang di depan mata di banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, ruang diskusi mahasiswa kini diawasi ketat. Setiap kegiatan yang bernuansa politik atau kritik sosial harus minta izin ke pihak rektorat, bahkan dengan daftar pembicara yang disetujui terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, kampus lebih menyerupai lembaga pemerintah yang menakutkan ketimbang ruang akademik yang membebaskan.
Situasi ini persis dengan yang digambarkan oleh George Orwell dalam Animal Farm A Fairy Story (1954) di mana, kampus memiliki semacam telescreen sebaga media propaganda sekaligus mesin yang mengawasi setiap gerak dan suara warga akademik secara terus menerus akibatnya kampus kehilangan ruang kebebsan dan berubah menjadi mesin kepatuhan. Mahasiswa didorong untuk disiplin administratif, bukan disiplin intelektual. Dosen dipaksa menulis manipulatif dan bohong terhadap dokumen untuk akreditasi, bukan untuk menggugat ketidakadilan. Hasil akreditasi kampus pun banyak diperoleh dari hasil kompromi dan lobi bukan karena objektifitas asesor. Kegiatan akademik diukur dari jumlah output, bukan kedalaman gagasan. Demokrasi pun mati bukan karena dilarang, tapi karena kehilangan tempat tumbuhnya keberanian berpikir.
Apatisme Mahasiswa dan Hegemoni Teknokrasi di Kampus
Saya juga menyoroti fenomena apatisme yang terjadi di kalangan mahasiswa karena kosongnya ruang diskursus akademik yang bebas. Kita harus jujur dan berani mengatakan bahwa mahasiswa generasi sekarang hidup dalam tekanan ekonomi, akademik, dan sosial yang berbeda dari masa sebelumnya. Saat saya kuliah di makasar banyak mahasiswa yang kreatif bekerja sambil kuliah, ada yang menjadi supir taksi, jual buku bahkan tukang becak dan uniknya mereka sama sekali tidak kenal gengsi. Tapi tapi jangan tanya soal disiplin, keteguhan belajar, berorganisasi dan prestasi mereka adalah kampiunya. Sebaliknya mahasiswa sekarang jauh dari buku, kurang minat baca dan jarang aktif di perpustakaan sehingga tidak memiliki peta paradigmatik dan kerangka konseptual yang mumpuni untuk menyusun postulat argumentasi.
Sebagai otokritik mahasiswa sekarang suka instan tidak senang melewati proses akademik panjang lebih mengejar gelar ketimbang meningkat bobot ilmu dalam diri. Mirisnya bahkan ada yang pilh jalan pintas agar cepat lulus, mereka menjauh dari dunia organisasi dan menganggap aktivisme kampus tidak produktif bahkan berisiko. Ini terjadi karena kampus tidak menyiapkan ruang dan atmosfir yang membudayakan berpikir analitik, kritis dan logik. Padahal kampus sebagai miniatur dari negara harus menjadikan ruang publiknya bebas meminjam istilah Juergen Habbermas (1962), yakni tempat mahasiswa dan dosen berkumpul secara bebas untuk berdiskusi, berdebat, dan membentuk opini publik yang rasional dan kritis. Kelompok-kelompok diskusi dan studi klub kampus harusnya dibiarkan tumbuh subur bersinergi dengan Bem dan UKM. Agar kreatifitas dan daya berpikir mahasiswa semakin terlatih dan tersalurkan bukannya dihambat dan disumbat dengan dalih pikiran kritis tidak sepenting skill.
Akibat cara pikir kampus yang ortodoks banyak pengetahuan-pengetahuan filosofis dan antropologis terasa asing bagi mahasiswa. Paradigma berpikir kritis yang disebut critical thinking di era modern sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendorong sikap terbuka, pengambilan keputusan yang baik, mengenali kesalahan berpikir dan logika tersembunyi dari kebijakan-kebijakan politik publik. Bagi saya menyempit dan menghilangnya ruang dialektika di kampus justru akan semakin menjerumuskan kampus pada feodalisme dan patronase akut. Praktek mikro demokrasi kampus berupa kebebasan bicara dan ekspresi harus terus hidup sebagai logos (akal) thymos (keberanian) dan epthymia (keinginan) yang deliberatif dalam terminologi Aristoteles. Jika rasionalitas tidak menjadi tumpuan berpikir dan berpikir kritis tidak menjadi metode ilmiah di kampus maka, bagi saya justru kampus sedang megubur dirinya sendiri dan memupuk budaya teknokratis bukan filosofis. Di mana kesuksesan diukur dari indeks prestasi saja, bukan dari keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.
Sehingga outcome pendidikan hanya akan menjadi proses produksi tenaga kerja massal bagi pasar kapitalis bukan pembentukan warga negara yang berpikir logik, kritis, dan rasional. Maka tak heran jika diskusi tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, atau korupsi justru lebih ramai di media sosial dari pada di ruang kuliah kampus. Saya pikir bahwa demokrasi kampus mati karena kehilangan warga intelektualnya sendiri yang kritis.
Kooptasi dan Komersialisasi Ruang Akademik
Saya gunakan istilah kooptasi untuk menggambarkan adanya pengambilalihan atau pembungkaman kekuatan kritis oleh kekuasaan dominan dan hegemonik negara terhadap otoritas akademik di kampus. Kooptasi terjadi dalam konteks akademik Ketika dosen, dan Lembaga riset kampus kehilangan otonomi ilmiah dan kebebsan mimbar akademiknya hilang karena adanya tekanan negara. Hal ini berimplikasi pada hilangnya fungsi kritis kampus sebagai ruang publik rasional dalam istilah Hebbermas, kampus kini rata-rata telah berubah menjadi instrumen kekuasaan politik yang tidak lagi aktif memproduksi dan serius membagun wacana emasipatoris. Saya amati bahwa isyarat dan tanda bencana kematian demokrasi kampus juga turut dipercepat oleh relasi kekuasaan yang tak sehat antara kampus dan negara.
Banyak perguruan tinggi kini bergantung pada bantuan pemerintah seperti program KIP kuliah, CSR industri, dan hibah-hibah riset, sehingga kampus cenderung menghindari kritik terhadap kebijakan publik. Peran kampus pun menjadi lunak, jinak dan transaksional. Rektor lebih pas disebut pejabat, bukan intelektual yang berani kritis, mahasiswa diperlakukan hanya sekedar target pasar dan pelanggan, bukan warga akademik yang dilatih dan diasah berpikir kritis untuk mengenali ketidakadilan, eksploitasi dan penyimpangan di sekitarnyandan dosen hanya menjadi buruh riset, bukan penjaga nurani bangsa. Mengapa ini terjadi, saya pikir tidak lepas dari praktek komersialisasi pendidikan mengubah wajah demokrasi kampus menjadi pragmatis.
Kritik sosial tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan akademik, melainkan ancaman terhadap citra institusi. Bahkan organisasi mahasiswa pun kini lebih banyak sibuk dengan kegiatan branding kampus daripada membela kepentingan publik. Demokrasi mati bukan karena dibunuh dari luar, tetapi karena dikhianati dari dalam oleh civitas akademiknya sendiri. Banyak proyek-proyek penelitian kampus diarahkan hanya untuk menghasilkan dana, bukan untuk kepentingan public tidak heran dunia Pendidikan tinggi modern berlomba-lomba menjual branding akademik melalui akreditasi padahal banyak aksi tipu-tipu dokumen palsu. Demikian, juga degan rangking-rangking dan peringkat kampus lebih sering menampilkan sisi simbolik dari pada isi dan bukan rahasia umum jika segala atribut dan peringkat bisa dibeli. Kampus kini telah kalah idealismenya karena tunduk pada logika keuntungan dan kooptasi oleh negara. Akibatnya ilmu pengetahuan kehilangan nilai moral dan sosialnya, karena menjadi alat produksi buruh murah bagi industry kapitalis.
Meneguhkan Kembali Nadi Demokrasi Demokrasi Kampus sebagai Barometer Bangsa
Salah satu yang paling kontras dari kematian demokrasi kampus adalah minimnya suara-suara kritis yang datang langsung dari rahim dan jantung kampus terhadap akses Pendidikan bermutu yang timpang. Untuk menjadi dokter bukan rahasia umum harus membayar ratusan juta sekedar untuk dapat tiket masuk, rasanya tidak adil namun, ini realitas. Sehingga di dunia kampus antara kooptasi kekuasaan negara dan praktek komersialisasi berjalan beriringan. Dalam pandangan saya bahwa kematian demokrasi paling fenomenal dan epik tentu terjadi di kampus-kampus swasta, selain tidak ada kebebasan mimbar akademik, tidak boleh ada suara berbeda dari pimpinan, tidak boleh ada protes atas ketidakadilan kebijakan. Nyaris, tidak ada dinamika perdebatan akademik yang alot soal kualitas pelayanan, kesejahteran, dan apresiasi yang rendah terhadap dosen dan mahasiswa, karena yang boleh ada dilanggengkan di kampus swasta hanya persetujuan dan anggukan bukan menggeleng menolak kebijakan yang tidak akademis dan humanis.
Sejatinya kematian demokrasi kampus bukanlah takdir, demokrasi kampus saya kira bisa dihidupkan kembali, jika civitas akademika berani merebut kembali makna pendidikan itu sendiri. Dosen harus kembali ke peran sejatinya sebagai pembimbing moral dan intelektual, bukan sekadar evaluator dan pengobral nilai. Mahasiswa mulai kini, perlu sadar bahwa mereka adalah agen penting perubahan, agen kontrol dan agen moral karenanya kampus bukan semata tempat mencari gelar bagi mahasiswa, tetapi medan perjuangan yang membentuk identitas dan karakter kedalaman juga keluasan ilmu pengetahuan yang berguna bagi bangsa. Bagi saya demokrasi kampus bisa dihidupkan kembali melalui sejumlah langkah-langkah sederhana namun bermakna, seperti menyusun ulang formulasi kurikulum dengan memberi porsi untuk menginsersi mata kuliah yang mendukung critical thinking di kampus seperti filsafat ilmu, pengantar filsafat, antropologi politik, sosiologi kritis dan etika serta filsafat moral. Selain itu, kampus perlu membuka ruang diskusi lintas ideologi, memberi kebebasan akademik yang nyata, dan menjamin hak berpendapat tanpa tekanan dan ancaman administratif. Pimpinan kampus harus sadar bahwa kebebasan berpikir bukan ancaman, melainkan sumber kemajuan.
Kampus yang demokratis tidak diukur dari seberapa megah gedungnya atau seberapa tinggi peringkat akreditasinya, tetapi dari seberapa besar ruang yang ia sediakan untuk berpikir bebas dan bersuara jujur. Kematian demokrasi kampus adalah cermin suram bagi masa depan bangsa. Sebab, dari ruang-ruang akademiklah lahir para pemimpin, birokrat, dan intelektual masa depan. Jika ruang itu mandul secara moral dan kritis, maka bangsa ini akan dipimpin oleh generasi yang patuh tapi tak berpikir, cerdas tapi tak berani. udah saatnya kampus bangkit dari kematian demokrasinya. Karena ketika kampus berhenti berbicara, bangsa pun kehilangan akalnya. (*)