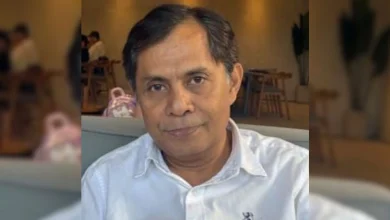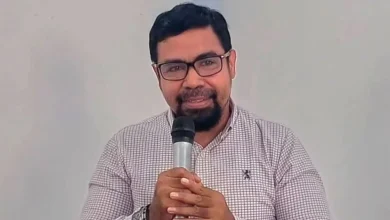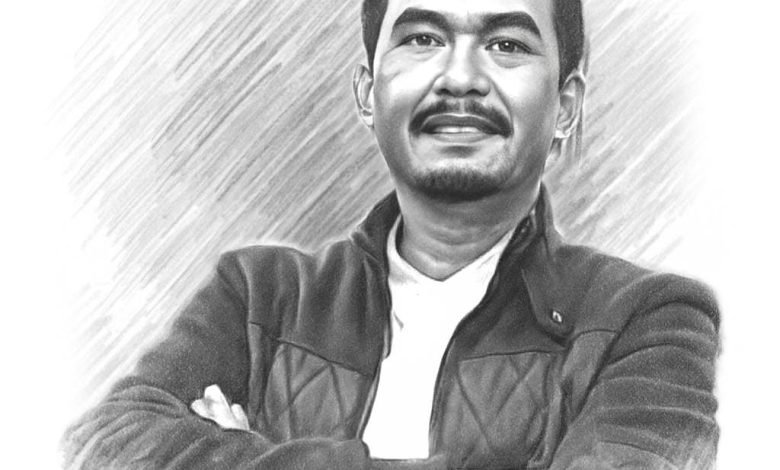
Oleh: Nurdin Ranggabarani – Direktur Eksekutif Matadata Institute
Beberapa pekan terakhir ini, jagat pemberitaan dan diskusi kita di daerah ini, diramaikan, oleh melambat, dan menurunnya angka agregat ekonomi kita, yang hanya tumbuh -0,82 persen, dan menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada urutan 37 dari 38 provinsi di Indonesia.
Rilis tersebut sontak membuat heboh. Berbagai ekspresi bermunculan. Ada yang prihatin, ada pula yang jingkrak kegirangan. Sementara yang lain mencemooh, ada pula yang menjudge. Pemerintah Provinsi pun dibikin sibuk mengumpulkan alasan, melakukan klarifikasi. DPRD NTB pun kemudian rapat, yang melahirkan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan relaksasi.
Permasalahan serupa, pernah terjadi di era pemerintahan NTB sebelumnya. Baik era TGB-BM, TGB-Amin, hingga Zul-Rohmi. Jika di era Iqbal-Dinda ini, kontraksi -0,82 persen, maka di era TGB pun pernah terjun bebas ke minus -2,69 persen (2011), dan minus -1,10 (2012). Demikian pula di era Zul, terpuruk kontraksi 0,62 persen (2020), dan di akhir masa jabatan 1,8 persen (2023).
Prestasi pertumbuhan pun, tak bisa kita sepelekan. TGB pernah mencatat pertumbuhan tertinggi rata-rata nasional, mencapai 7,1 persen (2018), dan Zul pada angka 6,95 persen (2021). Angka tersebut, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional saat itu, yang hanya 5,17 persen (2018), dan 3,69 persen pada 2021.
Namun saat ini, kami tidak sedang membicarakan kedua masalah di atas. Baik penurunan, maupun peningkatan, apalagi dalam bingkai kacamata dampak perekonomian daerah. Seperti daya beli, tingkat kesejahteraan, maupun multiplier fiskal lokal dan regional.
Karena peningkatan dan penurunan angka pertumbuhan ekonomi, adalah angka yang sangat fluktuatif dan dinamis. Bahkan, data naik-turunnya tersaji setiap bulan, per triwulan, per semester, per kuartal, hingga data tahunan.
Dan hal seperti itu, dapat diperperbaiki dengan stimulus fiskal dan kebijakan perekonomian daerah (seperti pengetatan arah belanja pemerintah, disiplin penyerapan anggaran, subsidi, bansos, dan operasi pasar, dan lain-lain) yang bersifat jangka pendek.
Namun data menyajikan, bahwa justru tidak terjadi permasalahan pada aktivitas ekonomi mayoritas masyarakat kita di sektor lain. Seperti pertanian, perikanan dan kelautan, industri kemasan dan UMKM. Kontraksi -0,82 persen semata-mata diakibatkan oleh melemahnya aktivitas sektor pertambangan kita di NTB.
Yang jika sektor pertambangan dipisahkan dari laporan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi NTB, masih pada angka 5,9 persen (Triwulan I, hingga Semester I, Year to Year 2025). Bahkan jika dihitung secara kuartalan (quarter to quarter), antara Triwulan I dan II, 2025 ini, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan angka positif, pada 6,56 positif.
Jika permasalahan kontraksi pertumbuhan ekonomi kita, akibat menurunnya aktivitas sektor pertambangan. Yang kemudian menjadi acuan menyeluruh, dalam memotret pertumbuhan perekonomian suatu daerah penghasil sumber daya alam tambang, hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mendasar.
Kita butuh telaah dan diskusi kritis. Ada apa di balik penyajian data seperti ini. Masih adakah nilai dan daya bargaining kita dengan SDA di daerah sendiri?. Bukankah ini bentuk “pressure framing” (pembingkaian tekanan) atau “hidden conspiracy” (konspirasi terselubung) tingkat tinggi, terhadap daya tawar daerah dalam hal eksploitasi SDA tambang?.
Lihatlah 3 provinsi urutan terbawah dalam rilis pertumbuhan ekonomi 2025 ini. Urutan terakhir, ditempati Provinsi Papua Tengah. Tempat dimana pegunungan Sudirman dan Grasberg, Kabupaten Mimika, dieksploitasi sejak 1972, oleh PT. Freeport Indonesia. Yang sangat terkenal dengan tambang terbesar dan terluas di Indonesia ini, mengalami kontraksi terparah hingga -9,83 persen, dan melempar provinsi tersebut ke urutan 38.
Disusul NTB, diurutan 37, tempat dimana tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, dikuras isi perutnya oleh PT. Amman Mineral, dan merupakan pertambangan terbesar kedua di negeri ini, mengalami kontraksi -0,82 persen, dan ketiga, Provinsi Papua Barat, tempat penambangan PT. Anugerah Surya Pratama dan beberapa konsorsium perusahaan tambang, yang menghancurkan Pegunungan Arfak dan merusak lingkungan Raja Ampat, diganjar kontraksi -0,23 persen.
Bukankah ini “politik data”, yang diskenariokan oleh para komprador eksploitir tambang, yang diselundupkan ke dalam kebijakan pemerintah pusat, untuk menjalankan “drama relaksasi”,dari satu episode ke episode berikutnya?.
Pertanyaan warasnya, apa salah para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, dan rakyat di daerah penghasil tambang, terhadap melemahnya kinerja sektor pertambangan di suatu daerah?. Bukankah larangan pengiriman (ekspor), diakibatkan oleh kesalahan mereka. Karena tidak mampu memenuhi tuntutan persyaratan regulasi, dan peraturan perundang-undangan?. Lantas kenapa, akibat kesalahan mereka, bukan mereka yang dinilai buruk, tapi kinerja perekonomian daerah yang dinilai terpuruk?.
Kita kadang terjebak dalam skenario drama, yang tak pernah kita kritisi. Jika di masa lalu, kita melawan kolonial bersenjata yang hendak merampas dan menjarah kekayaan negeri kita. Hari ini kita takluk, di bawah pressure angka-angka. Data dan angka hari ini, telah menjelma menjadi alat perang. Menjadi senjata dan peluru tanpa mesiu. Yang dapat ditembakkan dan diledakkan di semua medan pertempuran kepentingan. Siapa yang menggenggam data, maka ia mengendalikan dunia.
Demi agar para pengusaha tambang dapat segera menjual barang mentah mereka (tanpa harus mengindahkan ketentuan regulasi), dan segera mendapatkan keuntungan miliaran dolar, daerah harus ditampar dulu dengan angka-angka kontraksi yang mempermalukan. Agar para Kepala Daerah penghasil lebih mudah di-pressure, untuk menandatangani izin relaksasi ekspor.
Kita tidak lagi memiliki otoritas secuil pun untuk menjadikan SDA tambang sebagai kekuatan bargaining perjuangan. Misalnya membuat keputusan penghentian sementara, atau “boikot”, karena adanya suatu masalah misalnya. Bukankah relaksasi adalah wujud topeng pengingkaran dan bentuk pelanggaran telanjang terhadap UU Minerba, sebagai hukum nasional yang mesti dibela dan ditegakkan?.
Kita butuh keberanian Bupati, Walikota, dan Gubernur daerah penghasil se-Indonesia. Untuk bersatu, duduk bersama, dalam forum Asosiasi Daerah Penghasil Sumber daya Mineral Tambang, mendiskusikan “pressure framing” dan “hidden conspiracy”, dari pola penyajian data pertumbuhan dan penurunan perekonomian daerah ini. Untuk memisahkan sektor pertambangan secara tersendiri, dalam perhitungan pertumbuhan perekonomian daerah. Agar UU Minerba dapat kita tegakkan. Rakyat dan daerah tidak dirugikan. Serta kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat terselamatkan. (*)