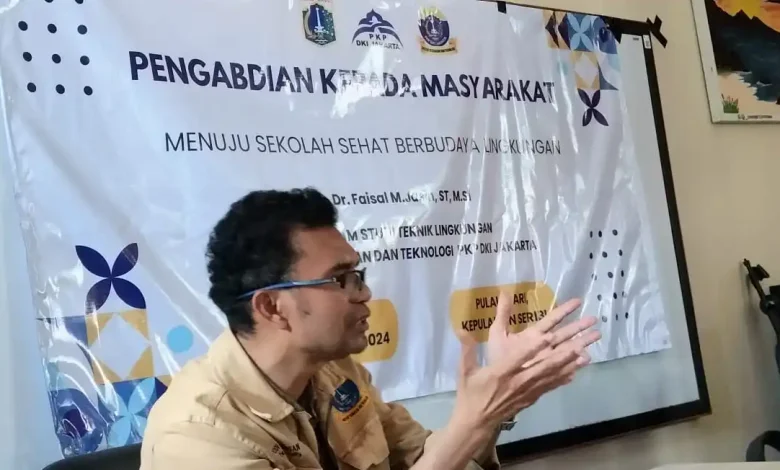
Oleh: Faisal M. Jasin*
Penulis berasal dari Bima, setiap lebaran selalu pulang kampung, dan menyaksilan diwaktu sore menjelang malam.
Di pasar kuliner ikan bakar, ada penjual, penikmat makanan, habis meminum air dengan botol plastik, menoleh kesamping, botol bekas air minum dibuang ke laut.
Begitu juga sebagian pedagang, habis berbenah sekantong plastik meletakan begitu saja di pinggir dan bahkan dicemplungkan ke laut, tempat sampah raksasa.
“Mau dibuang ke mana lagi, Pak?” katanya pasrah. Pemandangan ini bukan hal asing di Kota Bima.
Data terbaru mencatat timbunan sampah di Bima telah menembus 80 ton per hari, atau setara hampir 29 ribu ton per tahun.
Angka ini, bila dibayangkan secara visual, adalah gunung kecil yang terus tumbuh setiap hari di pinggir kota. Sebagian besar sampah masih ditangani dengan cara lama: diangkut, lalu dibuang.
Tidak heran bila tumpukan plastik kini tak hanya menyesakkan daratan, tetapi juga mulai mengalir ke Teluk Bima, merusak sektor perikanan dan pariwisata dua nadi kehidupan masyarakat.
Tumpukan itu bukan hanya masalah estetika. Plastik sekali pakai yang hanyut ke Teluk Bima menjerat perahu nelayan, merusak jaring, dan mengurangi hasil tangkapan.
Para pelaku pariwisata mulai khawatir, karena wisatawan yang datang ke pantai tidak ingin berenang di laut penuh sampah.
Kota Bima hari ini berdiri di persimpangan jalan. Pertumbuhan ekonomi dan geliat urbanisasi yang semakin pesat membawa berkah tetapi juga menghadirkan ancaman serius: sampah.
Pertanyaan besar pun menggantung di udara: Apakah kita akan membiarkan Bima terkubur sampah, atau menjadikannya peluang untuk perubahan?
Pengelolaan sampah bukan sekadar perkara teknis. Ia adalah cermin peradaban, ukuran sejauh mana sebuah kota menata masa depannya.
Jepang berhasil karena warganya terbiasa memilah sampah sejak dini, bahkan anak-anak sekolah sudah tahu perbedaan antara botol PET dan sampah organik.
Swedia lebih jauh lagi: 99 persen sampah di negeri itu diolah kembali, sebagian besar menjadi energi. Filipina menunjukkan kekuatan komunitas: gerakan lingkungan tumbuh dari kampung-kampung miskin, membalik narasi bahwa perubahan hanya mungkin dari atas.
Tetapi Bima tidak perlu menjadi Jepang, Swedia, atau Filipina. Bima harus menemukan jalannya sendiri sebuah jalan yang berakar pada kearifan lokal, sambil membuka diri pada pengetahuan global.
Di sinilah konsep BIMA SECURE menemukan relevansinya. BIMA, atau Branding Integrasi Masyarakat Aktif, menekankan bahwa warga bukan sekadar objek kebijakan, melainkan aktor utama. SECURE Sustainable, Educative, Circular, Urban, Responsible, Eco-friendly menjadi fondasi membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi.
Artinya, solusi tidak cukup dengan membangun TPA baru atau membeli alat berat. Solusi sejati harus menembus rumah-rumah, sekolah, pasar, dan kampung-kampung. Harus meresap ke dalam denyut sosial, menyatu dengan nilai yang telah lama hidup di masyarakat Mbojo: gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan.
Orang Mbojo, memiliki semboyan hidup: Maja Labo Dahu atau malu dan takut. Sebuah filosofi yang menekankan rasa malu bila berbuat salah, dan rasa takut bila melanggar aturan moral. Dalam konteks lingkungan, semboyan ini dapat diterjemahkan sebagai malu membuang sampah sembarangan, dan takut merusak alam yang diwariskan leluhur.
Di kampung-kampung, gotong royong masih menjadi denyut kehidupan. Warga saling membantu saat membangun rumah, memanen padi, atau memperbaiki jalan desa. Mengapa semangat itu tidak dihidupkan kembali dalam urusan sampah? Bayangkan jika setiap kampung punya hari “gotong royong sampah”, di mana warga bersama-sama memilah, mengompos, atau mendaur ulang.
Budaya Bima juga kaya dengan tradisi musyawarah. Dalam rapat kampung, warga membicarakan soal air, sawah, hingga hajatan. Maka wajar bila forum musyawarah itu diperluas membahas kebersihan lingkungan. Di sinilah nilai lokal bertemu dengan kebutuhan modern.
Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah memberi sinyal tegas: mulai tahun depan, peringkat Adipura tidak hanya mencantumkan kota-kota bersih, tetapi juga kota-kota kotor.
Ini artinya, Bima tidak hanya berisiko gagal meraih penghargaan, tetapi juga berpotensi dipermalukan di panggung nasional.
Emil Salim, ekonom lingkungan senior, pernah berujar, “Lingkungan bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan dari anak cucu.” Bila Bima tercatat sebagai kota kotor, maka bukan hanya pemerintah yang dipermalukan, tetapi juga generasi muda yang sedang menatap masa depan.
Label “kota kotor” bisa mencederai identitas kolektif. Bima, yang bangga dengan sejarah kesultanan dan budaya maritimnya, tentu tidak ingin tercatat sebagai kota yang gagal menjaga kebersihan dasar.
Namun krisis selalu menyimpan peluang. Bayangkan jika sampah plastik yang menumpuk bisa diubah menjadi bahan bakar melalui teknologi pirolisis skala kecil.
Bayangkan bila sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos untuk sawah dan kebun. Bayangkan bila bank sampah tumbuh di setiap kelurahan, bukan sekadar proyek seremonial, melainkan sistem ekonomi rakyat.
Swedia pernah memulai transisinya saat menghadapi krisis energi di tahun 1970-an. Filipina mengubah cara pandang melalui gerakan komunitas di kota Quezon. Jepang memulai dari hal kecil: disiplin memilah di rumah. Semua lahir dari titik krisis.
Maka Bima pun bisa.
Jika kita serius, BIMA SECURE dapat menjadi peta jalan yang bisa ditempuh Bima untuk keluar dari krisis sampah:
- Sustainable: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah jangka panjang, bukan solusi instan. Termasuk memperkuat regulasi lokal, memperbaiki TPA, dan mendorong ekonomi sirkular.
- Educative: Menjadikan sekolah, pesantren, dan Lembaga Pendidikan non formal lainnya sebagai pusat pendidikan lingkungan. Anak-anak diajari memilah, membuat kompos, hingga mendaur ulang sejak dini.
- Circular: Mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular. Sampah plastik jadi bahan baku industri kreatif; organik jadi pupuk; logam dan kertas kembali ke pasar.
- Urban: Menata ruang kota agar ramah lingkungan: lebih banyak taman, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan pasar yang higienis.
- Responsible: Menegakkan hukum secara adil. Denda bagi yang membuang sampah sembarangan, insentif bagi warga yang aktif memilah.
- Eco-friendly: Menggunakan teknologi ramah lingkungan: pirolisis plastik skala kecil, biogas dari sampah organik, hingga panel surya di TPA.
Roadmap ini hanya akan berhasil bila ada kemauan politik yang kuat dan partisipasi masyarakat yang nyata.
Isabella Lovin, mantan Wakil Perdana Menteri Swedia, pernah menulis: “Sampah bukanlah akhir, melainkan awal dari rantai nilai baru.” Pernyataan itu mengingatkan bahwa pengelolaan sampah bisa membuka peluang ekonomi dari energi terbarukan hingga industri kreatif.
Di Indonesia sendiri, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menekankan bahwa kunci ada pada komunitas. “Tanpa partisipasi warga, kebijakan hanyalah kertas kosong,” kata almarhumah Nur Hidayati, mantan Direktur Eksekutif WALHI Nasional. Kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak lahir dari proyek megah, melainkan dari komitmen kolektif.
Bima pernah melahirkan pahlawan nasional Sultan Muhammad Salahuddin, mengukir sejarah maritim, dan menjaga warisan budaya yang kaya. Maka tidak pantas bila nama Bima tercatat sebagai “kota kotor” hanya karena gagal mengelola sampah.
Kini, bola ada di tangan kita semua: pemerintah kota, masyarakat, akademisi, hingga generasi muda. Kita bisa memilih jalan mudah membiarkan sampah menumpuk, menerima label kota kotor atau memilih jalan terjal, yaitu mengubah krisis menjadi kesempatan emas.
Seperti kata pepatah Mbojo: maja labo dahu. Malu bila merusak warisan leluhur, takut bila menggadaikan masa depan anak cucu.
Bima tidak boleh menyerah. Bima harus membuktikan bahwa kota kecil di timur Indonesia bisa menjadi teladan nasional dalam mengelola sampah. Karena pada akhirnya, mengelola sampah bukan sekadar menjaga kebersihan, melainkan menjaga martabat.
*Penulis adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Institut Kesehatan dan Teknologi Jakarta dan Bidang Kerjasama Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah







