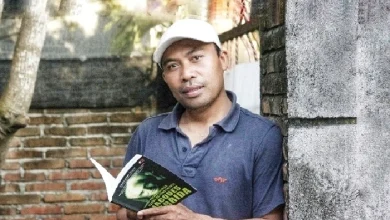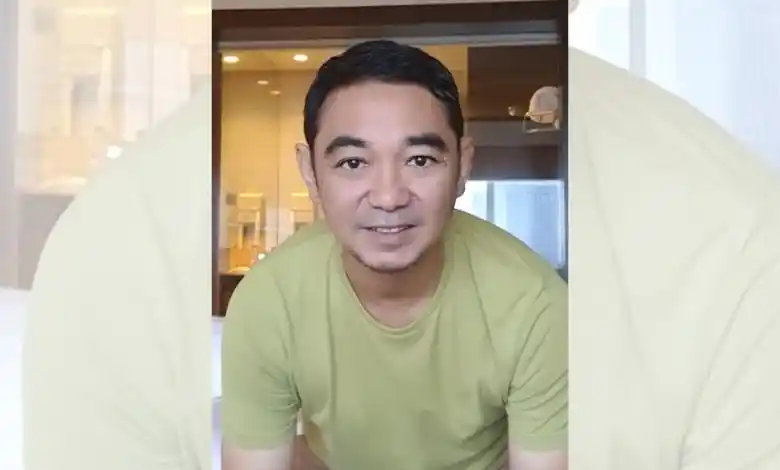
Oleh: Arie Nauvel Iskandar*
KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, seharusnya menjadi panggung diplomasi yang penuh kehormatan. Para pemimpin dunia berkumpul untuk membicarakan nasib Gaza, sebuah tanah kecil yang setiap harinya menjadi berita tentang kematian, bukan kehidupan. Indonesia, lewat Presiden Prabowo Subianto, hadir dengan tekad memperkuat posisi sebagai negara yang peduli pada perdamaian dan solidaritas kemanusiaan.
Namun, yang paling ramai dibicarakan dari forum itu bukanlah isi pidato, bukan pula hasil pertemuan, melainkan suara yang seharusnya tak terdengar publik. Mikrofon yang lupa dimatikan merekam percakapan ringan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prabowo. “Can I meet Eric?” tanya Prabowo. “I’ll have Eric call you. He’s such a good boy,” jawab Trump santai.
Sekilas, itu percakapan biasa basa-basi dua pemimpin negara di sela forum. Tapi dunia digital tidak mengenal konteks. Suara itu bocor, viral, dan berubah menjadi bahan diskusi global. Media internasional menyebutnya “a window into transactional diplomacy”, jendela kecil yang memperlihatkan wajah diplomasi yang terlalu manusiawi, bahkan mungkin terlalu pribadi.
Bahkan menjadi candaan di dalam acara Late Night Show yang di-host oleh Jimmy Kimmel belum lama ini, menandakan bahwa insiden ini telah menembus ranah budaya pop dan menjadi bagian dari percakapan publik global — dari ruang diplomasi hingga ruang hiburan.
Ketika Diplomasi Menjadi Terlalu Dekat
Diplomasi, di atas kertas, adalah urusan negara. Tapi pada praktiknya, ia dijalankan oleh manusia, lengkap dengan kelemahan dan sisi informalnya. Dalam satu detik percakapan tanpa naskah, seorang pemimpin bisa membangun citra baru atau menodai reputasi yang dibangun bertahun-tahun.
Prabowo datang ke KTT Gaza membawa simbol Indonesia yang aktif, berani, dan bersuara untuk kemanusiaan. Ia menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian dan ikut membangun Gaza pascaperang. Tapi simbol itu terganggu ketika publik lebih sibuk membicarakan percakapan pribadinya dengan Trump ketimbang pesan diplomatiknya.
Inilah dunia diplomasi hari ini dimana satu mikrofon yang lupa dimatikan bisa lebih kuat dari seribu pidato resmi.
Dalam teori komunikasi politik klasik, Harold Lasswell (1948) pernah merumuskan pertanyaan sederhana “Who says what, in which channel, to whom, and with what effect?” siapa berbicara, apa pesannya, lewat saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Di era media sosial, “saluran” tak lagi dapat dikontrol. Mikrofon yang lupa dimatikan bisa menjadi kanal baru yang menciptakan efek politik jauh di luar niat awal pembicaraan.
Antara Kepentingan Negara dan Jaringan Pribadi
Publik, tentu saja, berhak curiga. Ketika seorang presiden meminta bertemu anak seorang presiden lain yang juga dikenal sebagai pebisnis, aroma transaksional langsung menyeruak. Bukan karena ada bukti bahwa percakapan itu bermotif bisnis, tapi karena persepsi publik jarang menunggu klarifikasi.
Di era digital, opini dibentuk lebih cepat daripada fakta. Setiap potongan video adalah narasi, dan setiap narasi bisa mempengaruhi reputasi. Insiden ini pun memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara diplomasi dan jaringan personal.
James E. Grunig (1992) dalam Excellence Theory of Public Relations menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif antara organisasi termasuk pemerintah dan publik harus bersifat dua arah simetris yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika komunikasi diplomatik terperangkap dalam kesan personal, keseimbangan itu terganggu. Publik merasa ditinggalkan dari percakapan yang seharusnya mewakili mereka.
Indonesia punya sejarah panjang sebagai negara yang menjaga jarak dari politik kekuatan besar. Prinsip bebas-aktif bukan hanya jargon, melainkan identitas moral. Karena itu, ketika percakapan pribadi terdengar seolah menjajaki kedekatan personal dengan keluarga Trump, sebagian publik merasa gelisah. Ada kekhawatiran bahwa diplomasi yang sejatinya harus mewakili kepentingan nasional berubah menjadi diplomasi berbasis jejaring pribadi.
Menguji Kematangan Komunikasi Negara
Dari perspektif public affairs, insiden ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tapi juga ujian kedewasaan komunikasi negara. Di era mikrofon yang selalu menyala dan kamera yang tak pernah tidur, tidak ada lagi ruang “off the record” bagi pemimpin dunia. Setiap gerak, tawa, dan sapaan adalah pesan politik yang bisa ditafsirkan publik.
Lebih jauh lagi, gestur dan sikap pejabat publik di depan audiens internasional kini menjadi bagian dari komunikasi strategis itu sendiri. Cara duduk, arah pandangan, nada bicara, bahkan jarak tubuh terhadap pemimpin lain, akan menjadi simbol yang direkam kamera, diunggah, dibedah, dan disimpan dalam memori digital publik global. Di dunia yang serba transparan, bahasa tubuh adalah kebijakan luar negeri kedua.
Protokol, Komunikasi, dan Diplomasi di Era Transparansi
Bagi tim protokol dan komunikasi pemerintah, peristiwa ini seharusnya menjadi wake-up call. Dalam dunia di mana setiap mikrofon berpotensi menjadi media global, kesiapan teknis dan disiplin komunikasi bukan lagi urusan kecil, tetapi bagian dari strategi diplomasi.
Tim protokol perlu memastikan setiap detail teknis dikawal dengan presisi mulai dari posisi mikrofon, pengaturan ruang, hingga prosedur keamanan audio. Sementara itu, tim komunikasi sedapat mungkin perlu mengembangkan pre-briefing protocol bagi setiap pejabat negara sebelum memasuki forum internasional walaupun seringkali terhambat oleh kebiasaan pejabatnya, hal ini semacam gladi komunikasi untuk memastikan tidak terjadi adanya ucapan spontan yang berpotensi menimbulkan salah tafsir publik.
Selain kesiapan teknis, penting juga menumbuhkan awareness bahwa komunikasi publik adalah bagian dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Karl Deutsch (1963) dalam The Nerves of Government menulis bahwa sistem politik yang baik adalah yang mampu mengendalikan arus informasi dengan kesadaran penuh. Dengan kata lain, pemerintahan yang kuat bukan hanya diukur dari isi kebijakan, tetapi juga dari kecermatan dalam menyampaikan dan melindungi pesan.
Narasi Resmi sebagai Kewajiban Pemerintah
Karena insiden ini telah menjadi konsumsi publik global, pemerintah tidak bisa diam. Apalagi setelah Eric Trump menanggapi langsung dalam wawancara dengan Reuters di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia menjawab secara diplomatis bahwa “mungkin Presiden Prabowo hanya menyinggung karena Trump Organization sudah memiliki dua proyek besar di Indonesia.”
Pernyataan itu, walau terdengar ringan, memperluas ruang tafsir publik. Kini bukan hanya percakapan antar pemimpin yang disorot, tapi juga hubungan bisnis antara keluarga Trump dan mitra di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah wajib menyiapkan narasi jawaban resmi, bukan semata klarifikasi defensif, melainkan penjelasan yang memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai negara berdaulat dan profesional.
Ketiadaan narasi hanya akan membuka ruang bagi spekulasi. Sebaliknya, penjelasan yang terukur akan menunjukkan ketenangan dan kedewasaan politik. Publik domestik dan internasional perlu diyakinkan bahwa diplomasi Indonesia tidak dijalankan atas dasar jejaring pribadi, tetapi atas dasar kepentingan nasional dan etika kenegaraan.
Momentum untuk Berbenah
Ironisnya, insiden ini muncul di forum yang membicarakan perdamaian dan moralitas global. Barangkali ini pengingat bahwa diplomasi modern bukan hanya soal sikap politik, tetapi juga soal disiplin komunikasi. Di dunia yang transparan, moralitas bukan hanya diukur dari keputusan politik, tapi juga dari cara berbicara dan kepada siapa seseorang berbicara.
Mungkin publik terlalu keras menilai, atau mungkin memang pemimpin terlalu sering lupa bahwa setiap kata adalah pernyataan publik. Apa pun itu, insiden “mikrofon yang tak dimatikan” ini memberi pelajaran penting: di panggung global, diplomasi bukan hanya urusan kebijakan, tapi juga citra.
Reputasi, seperti kepercayaan, dibangun perlahan tapi bisa runtuh oleh satu detik kelalaian. Dalam hal ini, satu kalimat ringan di sela forum perdamaian sudah cukup membuat dunia kembali mempertanyakan arah diplomasi Indonesia.
Namun di sisi lain, inilah momen reflektif. Pemerintah bisa menjadikan insiden ini sebagai bahan koreksi untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik, membangun kedisiplinan media handling, dan memastikan setiap pesan diplomasi tak tercampur urusan personal. Karena di zaman di mana kamera lebih tajam dari pedang, kehati-hatian bukan lagi pilihan melainkan strategi bertahan.
Saya meyakini, peristiwa ini akan menjadi perhatian serius bagi tim protokol dan komunikasi pemerintah ke depan tidak hanya dalam aspek teknis dan keamanan, tetapi juga dalam pembentukan etika dan kesadaran baru tentang arti komunikasi kenegaraan di ruang publik global.
*Penulis:
Pengamat Kebijakan dan Komunikasi Publik, Ketua Umum Indonesia Public Affairs Community (IPAC), Anggota Dewan Pembina Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), Praktisi Public Affairs, Pegiat ESG dan HAM.