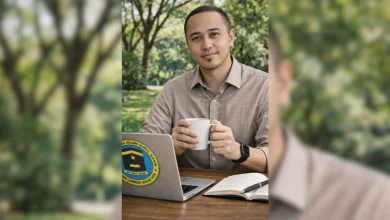Menjaga Kota Tepian, Menyelamatkan Laut Bima
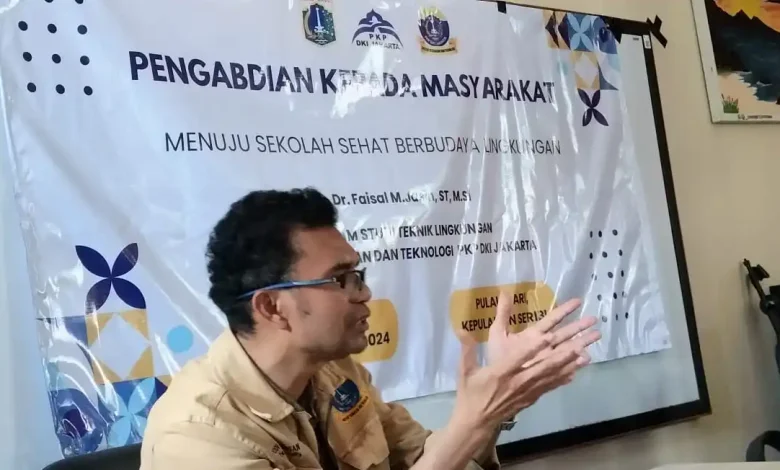
Oleh: Faisal M. Jasin, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta dan Bidang Kerjasama Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Laut adalah sumber pangan dan protein, pengaturan iklim dan oksigen, jalur transportasi dan perdagangan, sumber energi terbarukan, sumber daya mineral dan obat-obatan, rekreasi, pariwisata, kesehatan dan kesejahteraan, potensi ini yang dikelola oleh kota-kota pesisir dunia.
Dan laut selalu dipandang sebagai anugerah sekaligus tantangan. Begitu pula Bima, sebuah kota yang berdiri di tepian teluk, di ujung timur Pulau Sumbawa. Sebutan “kota tepian” bukan hanya penanda geografis; ia adalah identitas kultural dan historis. Dari tepian inilah lahir pelaut ulung, pasar ikan yang hiruk pikuk, dan tradisi maritim yang sudah berusia ratusan tahun. Tetapi dari tepian yang sama pula kini muncul ancaman: lautan yang kian dipenuhi sampah, pesisir yang tercemar, dan kota yang berisiko dicap sebagai salah satu kota terkotor dalam peringkat Adipura terbaru.
Bima adalah kota tepian. Tepian laut, tepian teluk, dan sering kali dianggap tepian dalam peta pembangunan nasional. Namun, justru pada “tepian” inilah denyut kehidupan terasa paling nyata. Laut menyediakan ikan, membuka jalur perdagangan, sekaligus menjadi benteng identitas masyarakat. Sayangnya, kondisi laut Bima kini tengah menghadapi krisis.
Pemandangan tumpukan plastik di tepi pantai, limbah pasar ikan yang mengalir ke teluk, hingga jaring nelayan yang tak jarang ikut mengangkat botol air mineral lebih banyak daripada ikan semuanya menjadi cermin dari persoalan yang tak lagi bisa ditunda.
Jika kita membaca Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN) 2023 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), setiap tahun Indonesia menghasilkan lebih dari 56,63 juta ton sampah, dan lebih kurang dari 3,2 juta ton di antaranya berakhir di laut. Kota-kota pesisir seperti Bima menjadi salah satu pintu masuk terbesar.
Dalam konteks Adipura, ancaman bukan hanya soal kebersihan jalan atau taman kota, melainkan juga kualitas ekosistem pesisir. Bima, dengan teluknya yang ikonik, bisa saja masuk ke daftar kota kotor jika masalah ini dibiarkan.
Di sebuah sore, ketika matahari condong ke barat dan perahu-perahu kecil kembali ke darat, anak-anak berlarian di pasir pantai. Mereka mencari kerang, bermain air, dan tertawa di tengah ombak kecil. Tetapi di sela permainan itu, tangan-tangan kecil mereka tak jarang memungut plastik sisa bungkus makanan, botol minuman, dan potongan styrofoam, ini nyata ketika anak saya berbisik kepada ibunya ketika memandang dari ujung tepian laut yang indah, bahwa ada sampah yang membuatnya tidak betah untuk berlama berlarian.
Anak-anak pesisir Bima tumbuh bersama sampah. Generasi yang seharusnya menyerap kearifan laut justru dibebani oleh warisan krisis ekologis. Pertanyaan sederhana muncul: apa yang akan mereka warisi jika kota tepian dibiarkan kehilangan lautnya yang bersih?
Di sinilah pentingnya melihat isu sampah bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah persoalan identitas, masa depan, dan bahkan moralitas. Bagi masyarakat Bima, yang hidup dengan falsafah Maja Labo Dahu malu dan takut berbuat salah sampah di pesisir seharusnya menjadi sumber rasa malu kolektif. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai pewaris tradisi maritim jika laut kita sendiri tercemar?
Profesor Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pertama, pernah berkata bahwa laut Indonesia adalah “lembaran masa depan” yang tidak boleh dirobek oleh plastik dan limbah. Pandangan itu sejalan dengan laporan terbaru UNEP (United Nations Environment Programme) yang memperingatkan bahwa polusi laut dapat mengurangi hasil tangkapan nelayan hingga 30 persen pada 2040.
Sementara itu, Hanif Faishol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup, saat aksi bersih-bersih di Pantai Kuta, Bali 5 Juni 2025 “Masalah sampah laut adalah tanggung jawab kita bersama. Aksi ini menjadi langkah nyata pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk melindungi ekosistem laut demi keberlanjutan generasi mendatang.” Pesisir bukan tempat sampah, melainkan halaman depan bangsa ini,” ujarnya.
Kutipan-kutipan ini relevan untuk Bima. Kota tepian tidak boleh lagi menjadi kota tepian dalam urusan kebijakan.
Bagaimana agar Bima tidak masuk daftar kota kotor dalam Adipura 2026 dan justru menjelma sebagai ikon kota pesisir bersih di Indonesia timur? Jawabannya ada pada peta jalan yang tidak sekadar teknis, tetapi berbasis identitas. Di sinilah konsep BIMA SECURE hadir: Branding Integrasi Masyarakat Aktif Sustainable, Educative, Circular, Urban, Responsible, Eco-friendly, yang pernah penulis sampaikan pada tulisan pertama.
Kerangka ini bukan sekadar jargon, melainkan strategi komprehensif.
Sustainable (Berkelanjutan): Bima harus menjadikan tepian lautnya sebagai pusat ekowisata: wisata mangrove, snorkeling terumbu karang, hingga kuliner laut yang bersih. Nelayan dapat diberdayakan sebagai “penangkap sampah laut,” di mana setiap kilogram sampah yang mereka kumpulkan dihargai. Dengan begitu, keberlanjutan ekonomi sejalan dengan keberlanjutan ekologi.
Educative (Pendidikan Lingkungan): Pesisir bisa menjadi sekolah terbuka. Anak-anak di pantai perlu dididik sejak dini untuk mencintai laut, bukan sekadar bermain di atasnya. Kurikulum lokal bisa memasukkan pelajaran tentang kebersihan laut, sementara ibu-ibu pesisir dilatih untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak langsung masuk ke laut.
Circular (Ekonomi Sirkular): Sampah plastik diubah menjadi kerajinan tangan, paving block, atau bahkan bahan bangunan alternatif. Sisa organik dari pasar ikan bisa diolah menjadi pupuk atau pakan ternak. Bank sampah pesisir dibangun sebagai simpul ekonomi baru, menjadikan tepian kota sebagai pusat inovasi sirkular, begitu juga dengan teknologi pengolahan sampah skala kecil, seperti teknologi firolisis untuk menghasilkan biosolar sebagai bahan bakar nelayan melaut.
Urban (Perkotaan Terintegrasi): Kebersihan pesisir harus menjadi bagian dari tata kota. Ruang publik di tepi teluk bisa menjadi ikon kota bersih: taman pantai, dermaga ramah lingkungan, dan pasar ikan bebas sampah. TPS 3R harus hadir di pelabuhan, memastikan bahwa sampah tidak lagi berakhir di laut.
Responsible (Tanggung Jawab Sosial): Budaya lokal harus menjadi mesin perubahan. Tokoh agama dapat menyampaikan khutbah tentang kebersihan laut, sementara tokoh adat menegaskan kembali nilai Maja Labo Dahu dalam konteks lingkungan. Regulasi tetap penting, tetapi harus diiringi kesadaran kolektif.
Eco-friendly (Ramah Lingkungan): Pasar ikan dan kawasan pesisir bisa menjadi pionir pasar tanpa plastik sekali pakai. Kemasan tradisional seperti daun pisang, bambu, atau wadah daur ulang bisa kembali digunakan dan ini mbojo bangat. Teknologi sederhana seperti komposter rumah tangga dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Jika kerangka ini dijalankan, Bima bisa membalik narasi: dari kota tepian yang terancam sampah menjadi kota tepian yang memimpin perubahan. Identitas geografis berubah menjadi identitas moral. Dari tepian teluk yang kotor, menjadi tepian yang bersih, indah, dan membanggakan.
Bayangkan Sofia turis asing dari spanyol yang dulu tidak nyaman ditepian laut bima ketika tiba Kembali di pelabuhan Bima. Alih-alih melihat sampah terapung, ia menyaksikan pantai bersih, pasar ikan tertata, dan anak-anak pesisir bermain di laut tanpa harus menghindari plastik. Bayangkan pula warga Bima yang berdiri dengan bangga menyebut kotanya bukan hanya sebagai kota tepian, tetapi sebagai ikon kota bersih pesisir Indonesia timur.
Bima punya modal besar: budaya yang kaya, laut yang luas, dan generasi muda yang penuh semangat dengan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bima 78,91 dari IPM Nasional 74,39. Tapi yang dibutuhkan hanyalah kemauan kolektif untuk mengubah krisis menjadi kesempatan.
Falsafah Maja Labo Dahu bisa menjadi energi moral. Malu membuang sampah sembarangan, malu membiarkan laut tercemar, dan takut merusak warisan generasi mendatang.
Kota tepian bukan kota pinggiran. Ia adalah halaman depan yang dilihat pertama kali oleh dunia. Jika Bima mampu menjaga lautnya, ia tidak hanya menjaga identitas, tetapi juga menulis janji baru: bahwa kota tepian bisa menjadi ikon kota pesisir bersih, berkelanjutan, dan bermartabat. Dan penulis mbojo akan setara dengan bali, lombok dan bahkan dunia lainnya, kita tunggu!.