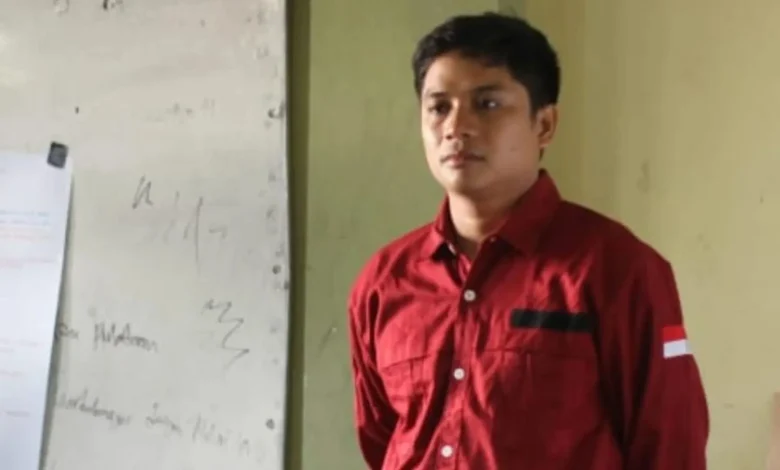
Oleh: Irwan – Mahasiswa Magister Ekonomi Unram
Gelombang keresahan tenaga honorer kembali menyeruak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua peristiwa besar dalam sepekan terakhir menegaskan betapa rapuhnya pasar kerja kita. Pertama, sebanyak 518 honorer Pemprov NTB terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Artinya, mereka otomatis tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu mulai 2026. Alternatif yang ditawarkan pemerintah hanyalah opsi outsourcing atau alih daya dengan status kerja lebih rentan.
Kedua, pada Kamis, 18 September 2025, ratusan guru honorer swasta dan pondok pesantren di Kabupaten dan Kota Bima turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bima dan Kantor Kementerian Agama, menuntut agar diangkat menjadi PPPK. Spanduk-spanduk yang dibentangkan berisi pesan getir: guru swasta adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi negara justru menutup jalan bagi mereka untuk mengakses kesejahteraan yang sama dengan guru negeri.
Dua kasus ini bukanlah insiden terpisah. Keduanya adalah potret dari problem struktural ketenagakerjaan kita: ketika negara lebih sibuk menertibkan regulasi administratif ketimbang menghadirkan keadilan substantif bagi para pekerja pendidikan.
Kerapuhan Job Security Honorer
Dalam teori ketenagakerjaan, job security adalah pondasi produktivitas. Tenaga kerja yang memiliki kepastian kerja cenderung lebih fokus, loyal, dan berkinerja baik. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan status rapuh mudah di-PHK, tidak ada jaminan sosial, upah rendah akan terjebak dalam siklus insecurity.
Itulah realitas honorer di NTB. Guru swasta dan tenaga non-ASN mengabdi bertahun-tahun, tetapi ketika regulasi baru lahir, mereka terancam tersingkir hanya karena tidak masuk database. Bahkan, negara meminta mereka “mencari pekerjaan lain”. Pernyataan ini jelas melukai hati para honorer yang sudah berpuluh tahun mengisi kekosongan di kelas-kelas pelosok.
Ironinya, ASN dan PPPK menikmati perlindungan penuh dengan hak dan fasilitas. Situasi ini selaras dengan apa yang disebut dual labor market theory: pasar tenaga kerja yang terbelah antara sektor formal yang terlindungi dan sektor informal yang tereksploitasi.
Human Capital yang Diabaikan
Jika ditilik dari perspektif human capital theory, guru honorer, baik negeri maupun swasta, adalah aset penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau fasilitas, melainkan tentang kualitas tenaga pengajar.
Mengabaikan guru swasta dan honorer sama dengan meremehkan investasi jangka panjang pada generasi bangsa. Bagaimana mungkin Indonesia berbicara soal bonus demografi dan daya saing global, sementara mereka yang berada di garis depan pendidikan justru hidup dalam ketidakpastian?.
Alih-alih dipandang sebagai beban anggaran, tenaga honorer seharusnya dianggap sebagai modal pembangunan. Sejahteranya guru berarti berkualitasnya pendidikan, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan produktivitas ekonomi bangsa.
Negara yang Absen
Kasus honorer di NTB menunjukkan wajah negara yang lebih sering hadir sebagai pengatur administrasi daripada pelindung rakyat. Honorer yang tidak tercatat dalam database diperlakukan seolah tidak pernah ada. Guru swasta diminta bersabar menunggu regulasi yang tak kunjung datang.
Padahal, teori labour market regulation menegaskan bahwa pemerintah wajib menciptakan aturan main yang bukan hanya efisien secara fiskal, tetapi juga adil secara sosial. Jika efisiensi dijadikan alasan untuk menyingkirkan honorer, maka negara sedang mengorbankan keadilan demi angka-angka.
Ketika pemerintah hanya menjadi penonton, pekerja pendidikan yang paling berjasa justru dibiarkan berjuang sendirian.
Arah Solusi: dari Regulasi ke Implementasi
Kedua kasus di NTB memberi pelajaran bahwa masalah honorer tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam. Ada beberapa langkah mendesak yang harus ditempuh pemerintah:
1. Integrasi Data Honorer Nasional
Seluruh tenaga honorer harus diverifikasi ulang dan dicatat secara transparan. Tidak boleh ada lagi pekerja yang “hilang” hanya karena kesalahan administratif.
2. Regulasi Afirmasi bagi Guru Swasta dan Ponpes
Pemerintah pusat, terutama Kementerian Agama, harus mengeluarkan regulasi atau Keppres yang membuka akses seleksi PPPK bagi guru swasta dan pesantren dengan standar seleksi yang adil dan realistis.
3. Skema Transisi dan Safety Net
Bagi honorer yang tidak bisa langsung diangkat PPPK, harus ada jaminan transisi berupa pelatihan ulang, sertifikasi, hingga skema outsourcing yang manusiawi dengan perlindungan upah dan jaminan sosial.
4. Reorientasi Anggaran SDM
Pemerintah daerah harus memandang pengangkatan honorer bukan semata beban belanja pegawai, melainkan investasi SDM jangka panjang. Dukungan fiskal dari pusat perlu diarahkan untuk menjamin hal ini.
5. Transparansi dan Partisipasi Publik
Proses seleksi PPPK harus terbuka dan bisa diawasi publik. DPRD, organisasi guru, dan masyarakat harus dilibatkan agar tidak ada diskriminasi baru yang lahir.
Terakhir penulis ingin sampaikan bahwa PHK honorer Pemprov NTB dan demonstrasi guru swasta Bima adalah cermin yang memantulkan wajah buram kebijakan tenaga kerja kita. Mereka yang paling berjasa justru dibiarkan tanpa perlindungan. “Negara hadir dengan regulasi, tetapi absen dalam keadilan”. Jika pembangunan manusia benar-benar menjadi prioritas, maka pemerintah harus segera berhenti memperlakukan honorer sebagai beban. Mereka adalah investasi bangsa.
Kita hanya bisa berharap, kasus di NTB menjadi titik balik: bahwa negara tidak lagi absen, melainkan benar-benar hadir untuk melindungi, menghargai, dan mengangkat martabat tenaga honorer yang telah lama menjadi pilar pendidikan di pelosok negeri. (*)






