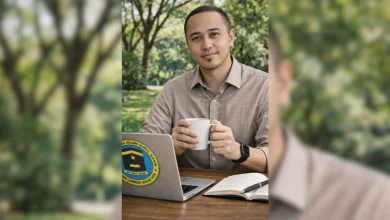Oleh: Dr. Alfisahrin, M.Si. – Staf Ahli DPD RI, Dosen UNBIM dan Fisip Upatma-Mataram
Wacana tentang matinya demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini sering nyaring terdengar, demokrasi yang dahulu dengan gigih dan berdarah-darah diperjuangkan melalui reformasi 1998 kini seolah kehilangan roh dan substansinya.
Demokrasi sering dipuja sebaga sistem yang paling adil dan manusawi, namun tidak berarti tanpa bahaya, menyanjung demokrasi secara buta tanpa memamahami secara kritis dan mendalam justru menjebak kita pada eufimisme (pemujaan) berlebihan.
Dalam pusaran politik kontemporer Indonesia, demokrasi lebih sering ditafsirkan sebagai ritual lima tahunan ketimbang etika hidup berbangsa. Harus diakui bahwa tanda-tanda kematian demokrasi telah lama menjadi alarm dan perhatian serius dari banyak pakar yang mengendus terjadinya gejala-gelaja kemerosotan demokrasi yang disebut demosida.
Pada banyak kasus, demokrasi tidak mati dengan senapan di pelipis, namun, demokrasi perlahan dibunuh dalam senyap, oleh tangan-tangan elite yang justru mendapat kuasa melalui mekanisme demokrasi.
DPR main proyek, DPR minta fee, DPR jual beli pokir dan DPR jual beli suara melalui serangan fajar di musim pemilu. Praktek curang semacam inilah yang disebut oleh pemikir seperti R. J. Rummel (1980) sebagai demosida yakni kematian demokrasi oleh pelaku dari dalam sistem.
Demosida bukan kudeta berdarah, pembubaran parlemen dan larangan pemilu, demosida justru menjelma manis dalam retorika populis elite, legalitas penguasa yang direkayasa seperti kasus ijazah palsu Presiden Jokowi dan rekayasa aturan MK untuk muluskan jalanya Wapres Gibran dan praktek politik yang mengebiri institusi pengawas pemilu adalah demosida.
Dalam demosida, demokrasi dibunuh secara legal dan sah oleh suara mayoritas, oleh undang-undang dan bahkan oleh hasil pemilu. Demokrasi kita, memang secara prosedural masih hidup, ada pemilu, ada partai politik, ada parlemen namun telah kehilangan ruh, integritas, keberanian dan kepercayaan dari publik.
Kebebasan sipil semakin dipersempit karena menjaga stabilitas, rakyat pun sering direpresi, penegakan hukum tebang pilih, partai politik berubah menjadi mesin kapitalis kekuasaan bukan kendaraan aspirasi yang menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Fenomena timpang demokrasi di negara yang tengah berlangsung saya kira bukan karena kesalahan teknis, melainkan konsekuensi dari politik yang elitis, kapitalistik, dan oligarkis. Tentu ini berdampak serius, jika oligarki terus mengatur penuh jalan dan pergantian kekuasaan akan berdampak pada semakin sulitnya akses kekuasaan bagi rakyat kecil.
Sirkulasi elite pun sebagai mekanisme demokrasi menggilirkan mandat kekuasaan kepada publik lagi-lagi hanya akan dinikmati segelintir elite. Demokrasi pun menjadi sekedar formalitas dan demosida pun menjadi tidak terelakan.
Sehingga perlu kewaspadaan terus-menerus melalui kontrol dan partisipasi kritis publik dalam mengawal demokrasi dan tidak boleh diserahkan penuh kepada politisi. Alexis De Tocquvile (1853) pemikir kenamaan Prancis dengan tegas menyatakan bahwa dibalik janji manis demokrasi mengandung benih-benih tirani baru yakni tirani mayoritas, birokratisasi yang kaku, serta reduksi kebebasan menjadi sekedar angka-angka elektoral.
Demokrasi memang sistem yang unik karena menjanjikan kesetaraan, mobilitas sosial, dan partisipasi politik namun, realitasnya di Indonesia justru demokrasi menjadi jalan legal bagi tumbuh suburnya praktek nepotisme, kolusi dan korupsi. Patologi birokrasi lama dan klasik namun, terus saja hidup meski telah ada reformasi dan berganti-ganti kuasa.
Bagi Alexis de Tocquivile (1853) dalam Democracy in America percaya bahwa demokrasi adalah takdir modernitas dan sistem politik yag tidak terhindarkan. Demokasi hanya bisa bertahan bila ditopang oleh civic virtue yakni keutamaan warga negara.
Bagi saya demokrasi bukan hanya sekedar perkara enteng sekedar memilih wakil, melainkan urusan rumit, tentang siapa yang menjadi wakil, ekosistem dan tradisi memiih wakil yang berkualitas (rasional voter) harus menjadi kebiasaan yang hidup dalam keseharian.
Demokrasi hanya bisa hidup bila ada keterlibatan warga negara, komunitas, solidaritas, kepercayaan sosial dan kebebasan bicara publik yang dipelihara oleh negara. Namun, demokrasi di Indonesia menjungkirbalikan prinsip sipil nya sendiri dengan mempersempit partisipasi menjadi sekedar cap jempol di bilik TPS saat pemilu dan pilkada.
Warga negara diarahkan hanya menjadi konsumen politik, bukan produsen gagasan tentang kelayakan dan kredibilitas orang yang akan dipilih. Media sering menjadi pentas kebencian bukan wadah netral yang mendidik dan mencerahkan, institusi negara dan pemilu kian gemuk oleh belitan regulasi tetapi keropos dalam pelayanan.
Situasi ini digambarkan oleh Alexis de Tocquivile (1853) dengan ‘despotisme lembut’ yakni masyarakat yang tampak bebas, namun sesungguhnya dikendalikan oleh aturan, angka, dan elite yang tak tersentuh. Di tengah euforia perayaan demokrasi yang memenangkan secara telak atas komunisme, sosialisme dan ateisme, demokrasi sukses menjadi sistem politik mayoritas di hampir dua ratus negara dunia.
Oleh Francis Fukuyama dalam The end histori and the last man, diprediksi akan menjadi ideologi akhir yang bertahan diantara banyak ideologi global. Robert Dahl dalam Poliyarchi (1971) menjelaskan bahwa keunggulan demokrasi sehingga digemari secara universal oleh banyak negara karena demokrasi menjamin kebebasan dan perlidungan hak azasi, mekanisme pergantian kekuasaan yang damai, kontrol rakyat terhadap pemerintah, kesetaraan politik, dan pendidikan politik serta partisipasi publik yang luas.
Keunggulan demokrasi terletak pada kompetisi yang fair, partisipasi luas. Namun, sejak kemunculan Steven Levitski dalam How Democracies Die (2018), demokrasi tidak selalu mati dengan dentuman tank di jalanan atau kudeta berdarah, demokrasi bisa sekarat perlahan, nyaris tanpa kita sadari, lewat mekanisme sah yang di lembagakan misalnya oleh pemimpin yang lahir lewat pemilu.
Tanda-tanda kritis akan kematian demokrasi di indnesia diawali dengan pelemahan oposisi, polarisasi politik yang kian tajam, dan normlisasi praktek politik dinasti juga aligarki. Masa depan dan kelangsungan demokrasi tidak hanya ditentukan hanya dengan aturan tertulis. namun, membutuhkan dua norma tidak tertulis Yakni mutual tolerance (toleransi antar elite) dan institutional forbearance (kesabaran politk untuk tidak menghabisi lawan meski secara hukum memungkinkan.
Dalam konteks politik dan demokrasi Indonesia, dua norma ini semakin tipis, polarisasi politik berbasis identitas budaya dan agama semakin kental, memudarkan toleransi politik, sementara elite kian gemar memakai celah hukum demi menyandera dan memperkuat cengkraman kekuasaan terhadap rival politik. Pada konteks inilah Tocquivile mengingatkan agar warga negara kritis bukan pasif, aktif bukan sekedar mengikut arus tetapi kritis menolak aneka bentuk arogansi dan dominasi elite-negara.
Demosida dalam Praktik Kekuasaan
Demokrasi Indonesia sedang berada dipersimpangan, telah lebih dari dua dekade reformasi, sitem politik yang pernah dirayakan sebagai The Third largest democracy in the world kini justru memperlihatkan pelapukan dari dalam. Kondisi ini disebut dengan democratic erosion. Demosida bukan sekedar pembunuhan fisik rakyat, melainkan peminggiran kedaulatan rakyat dalam proses politik.
Saya mencatat sejumlah praktek demosida yang terus berlangsung dalam kehidupan demokrasi kita seperti manipulasi aturan main dari UU pemilu dan revisi UU KPK. Lembaga-lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM pun perlahan kehilangan taring karena intervensi politik.
Dalam Electoral Malpractice (2011) bahwa demosida seringkali terjadi dalam bentuk manipulasi adminstrasi yaitu penggunaan birokrasi atau instrumen negara untuk menguntungkan kandidat atau partai politik tertentu.
Model dari praktik demosida lain yakni manipulasi legal suatu perancanagn undang-undang pemilu yang bias, seperti aturan ambang batas yang membatasi representasi politik dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia calon presiden/wakil presiden, membuka jalan lepnag bagi Gibran yang kala itu belum berusia 40 tahun lolos menjadi wapres.
Dalam perspektif Sarah Birch (2011) kasus Gibran bukan sekedar soal individu, melainkan cermin rapuhnya integritas elektoral di Indonesia dengan menggunakan cara manipulasi legal. Di era demokrasi kontemporer electoral malpractice (mal praktek pemilu) terjadi berulang dan masif setiap perhelatan pemilu, ini menjadi contoh bagaimana aturan hukum, lembaga, dan praktik politik dapat dimanipulasi untuk kepentingan elite.
Raphael Lemkin (1944) memaknai demosida secara metaforis untuk menjelaskan proses erosi demokrasi yang berarti pembunuhan rakyat oleh negara secara fisik lawan dari genosida yang diartikan sebagai destruction of a nation or an ethnic group. Dengan menggunakan perspektif Lemkin, kita bisa memahami bahwa genosida berupaya memusnahkan identitas kolektif suatu etnis dari suatu bangsa sedangkan demosida politik berupaya memusnahkan hak politik rakyat.
Saya melihat bahwa demokrasi Indonesia seringkali berhenti pada tataran prosedur, pemilu dilaksanakan secara reguler setiap lima tahun, partai politik ikut berkontestasi dan rakyat diberikan hak suara. Namun, substansi demokrasinya memudar. Pilihan rakyat kerap diarahkan oleh kekuatan modal, media, dan oligarki.
Pemilu menjadi gelanggang pesta elite, bukan lagi ruang artikulasi dan agregasi aspirasi rakyat. Ruang-ruang partisipasi publik bahkan dapur inti kekuasaan pun, kini dikuasai dan dikendalikan oleh oligarki termasuk partai politik dan kebijakan politik negara.
Ironisnya, oligarki pun mampu menekan, mendikte dan mempengaruhi sejumlah Keputusan politik negara dengan membentuk aturan yang hanya menguntungkan oligarki. Akhirnya demokrasi yang seharusnya menjamin kesetaraan (egalitarian) berubah menjadi sistem feodalisme baru dalam kemasan modern.
Padahal, demokrasi hidup dari kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat. Namun, kini ruang-ruang partisipasi dan kritis publik tersebut, telah diambil alih oleh oligarki yang menumpang hidup dalam tubuh kekuasaan. Kesadaran kritis publik dimanipulasi dan dijinakan dengan aliran bantuan bansos, aktivis sipil direpresi oleh intimidasi aparat negara.
Masa depan demokrasi semakin terjal berliku karena dibelit oleh pragmatisme elite, pada konteks ini, kelangsungan hidup demokrasi sangat bergantung pada keberanian publik dan kesadaran sipil menggugat aneka penyimpangan kekuasaan.
Saya menyaksikan praktek demosida nyaris terjadi di semua sektor kunci kehidupan inti demokrasi, KPU, Bawaslu, Panwaslu, bahkan KPPS kini, semakin diragukan integritas dan netralitasnya karena disandera oleh aneka titipan kepentingan elite.
Apa yang terjadi dengan anomali demokrasi yang merebak luas, Tentu rakyat semakin kecewa dan menjauhi politik. Kasus OTT KPK Immanuel Ebenezer, Wamen Kemenaker terlihat semakin memicu reaksi negatif publik terhadap janji pemberantasan korupsi yang semakin setengah hati.
Praktek nepotisme melalui politik dinasti yang mengakar dan menjalar liar ke seluruh penjuru negeri harusnya sudah cukup menjadi bukti kuat bahwa demokrasi di Indonesia telah mengarah ke proses democratic backsliding yakni kemunduran demokrasi secara perlahan-lahan, Di mana sejumlah institusi dan perangkat demokrasi tetap ada, namun, isinya telah kosong karena azas, prinsip dan filosofi demokrasi tidak lagi hidup sebagai tata nilai berdemokrasi. (*)