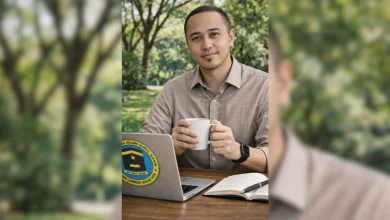Gen Z: Kekuatan Politik Baru?

Oleh: Widodo Dwi Putro – Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Lima tahun lalu, pertanyaan setengah meremehkan: “Apakah Gen Z peduli politik?” masih menjadi perdebatan hangat. Hari ini, pada Agustus – September 2025, pertanyaan itu sudah tidak relevan. Generasi yang sering dituduh cuma bisa rebahan, ngegame, bikin meme dan konten di media sosial ini telah membuktikan diri sebagai kekuatan kontrol politik baru yang tak terduga, dari gawai hingga turun ke jalan mengubah lanskap kekuasaan di Jakarta dan Kathmandu.
Berbeda sewaktu saya mahasiswa (angkatan 1990-an), kalau mau demo, perlu korlap, mobilisasi massa dengan megaphone di perempatan jalan. Itu pun, perlu pra-kondisi membangun kesadaran massa yang membutuhkan waktu lama dengan live in di basis petani, buruh, dan kaum miskin kota. Hari ini? Cuma perlu kuota internet dan satu tweet yang viral.
Mobilisasi Dengan Gawai
Di Indonesia, kita telah menyaksikan bagaimana Gen Z menguasai medan pertempuran politik non-konvensional. Mereka tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga secara aktif mengendalikan narasi dan kebijakan. Ingat kembali pada insiden yang terjadi beberapa minggu lalu, ketika wacana tunjangan mewah anggota DPR mencuat ke publik. Alih-alih menunggu media utama atau elit politik untuk bersuara, gelombang protes digital yang dimotori Gen Z langsung membanjiri media sosial.
Dengan infografis yang estetik, meme yang satir namun edukatif, dan tagar yang viral dalam hitungan jam, mereka berhasil mengorkestrasi tekanan publik yang masif. Aksi tersebut bukan hanya sebatas trending topic sesaat.
Kekuatan mobilisasi digital dan aksi turun ke jalan ini memaksa DPR untuk memangkas atau bahkan membatalkan sebagian tunjangan tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan tidak lagi eksklusif milik mereka yang duduk di kursi parlemen, melainkan juga dimiliki oleh jutaan jari yang menekan tombol retweet dan share.
Ini menunjukkan bahwa Gen Z bukan lagi sekadar penonton pasif. Mereka adalah kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Mereka tidak takut menantang status quo, dan mereka punya cara baru untuk berjuang yaitu, dengan menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Mereka menggunakan media sosial untuk membangun solidaritas, menyebarkan informasi, dan menyerukan aksi.
Desentralisasi Kekuasaan: Kekuatan Narasi di Atas Senjata
Di ranah yang lebih ekstrem, seperti yang kita lihat di Nepal, kekuatan kolektif Gen Z bahkan mampu menjadi katalisator bagi tumbangnya rezim otoriter dan hedon. Meskipun sejarah revolusi di Nepal jauh lebih kompleks, peran kaum muda — yang kini bisa kita identifikasi sebagai bagian dari Gen Z dan milenial — sangat krusial. Mereka menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang dibungkam.
Mereka membuktikan bahwa di era informasi digital, kontrol kekuasaan tidak lagi diukur dari berapa jumlah senjata dan pasukan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan untuk membangun narasi yang paling menarik dan viral. Setiap like, share, dan komentar adalah bentuk persetujuan, dan akumulasi dari interaksi-interaksi digital ini bisa berubah menjadi kekuatan politik yang riil dan tak terbendung oleh rantis dan gas air mata.
Mengapa Elite Gagal Menangkap Pesan Gen Z?
Siapakah Gen Z yang menjadi subjek politik baru ini? Menurut pemikir liberal, John Locke, bahwa subjek politik adalah individu otonom yang mengambil keputusan rasional. Sementara dalam Marxisme, sokoguru revolusi adalah kelas proletariat yang berjuang melawan penghisapan kelas atas. Gen Z melampaui kedua definisi ini. Mereka tidak terbentuk dari identitas kelas atau afiliasi partai, melainkan dari solidaritas afektif dan digital.
Mereka bersatu bukan karena satu ideologi kaku, tetapi karena kemarahan kolektif terhadap ketidakadilan yang mereka saksikan dan rasakan. Meme menjadi bahasa politik universal mereka—sebuah bahasa yang melampaui batas geografis dan sosial, mengomunikasikan kritik dengan cara yang ringan namun menusuk.
Solidaritas mereka adalah solidaritas pascamodern; ia cair, sementara, dan seringkali didefinisikan oleh isu-isu spesifik ketimbang manifesto besar. Mereka adalah subjek politik yang dibentuk oleh pengalaman bersama dalam jaringan, di mana identitas politik seringkali sama cairnya dengan identitas digital.
Gen Z mengajarkan kita bahwa politik adalah tentang isu, bukan hanya tentang figur. Beberapa influencer diundang ke kantor pemerintah untuk sesi foto dan jabat tangan. Atau, influencer dijadikan staf khusus menteri untuk menetralisasi isu dan menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat. Pesannya adalah “Kami telah mendengarkan suara kalian,” namun bagi Gen Z, ini adalah “pertunjukan wayang di era digital.” Mereka menganggapnya sebagai “tokenisme,” yaitu upaya pencucian citra dengan menggunakan wajah-wajah influencer.
Pendidikan gen Z makin tinggi, tapi makin susah untuk mendapat pekerjaan. Sebagian dari mereka menjadi prekariat dengan ketidakpastian pekerjaan, tanpa jaminan sosial atau hak-hak pekerja yang memadai. Sebagian lagi, terperangkap dalam barisan pengangguran yang panjang.
Sementara para elite yang umumnya berusia mapan, justru memamerkan kekayaannya dan tidak peka dengan menaikan berbagai tunjangan mewah di tengah kesulitan. Ketika dikritik, respons elite politik mulai dari yang menyampaikan janji seperti kalimat “Kami mendengar suara kalian” atau “Ini akan kami kaji mendalam.” Bagi Gen Z ini merupakan “retorika kosong” karena mereka dapat dengan mudah mencari (searching) arsip janji serupa yang tidak pernah terealisasi dari jejak-jejak digital. Ini adalah bukti nyata bahwa cara-cara “pembodohan” lama tidak lagi relevan.
Dalam konteks aksi di Indonesia dan Nepal di bulan Agustus – September 2025, kita melihat bagaimana rezim otoriter berusaha menguasai narasi dengan sensor dan propaganda. Namun, upaya itu tak berdaya di hadapan ribuan narasi tandingan yang menyebar secara organik melalui jaringan digital. Sebuah video amatir bisa lebih dipercaya daripada siaran berita resmi pemerintah, dan sebuah unggahan di media sosial bisa menjadi bukti yang lebih kuat daripada pernyataan pemerintah.
Kemarahan gen Z yang berbasis data seringkali disederhanakan sebagai masalah hoaks atau “ah, itu khan hanya kritik segelintir orang”. Ini adalah bentuk “gaslighting” yang sangat menghina bagi mereka.
Kemudian, ada pengerahan buzzer untuk melancarkan narasi positif bahwa kritik itu tidak benar, juga melaporkan akun-akun kritik itu secara hukum. Alih-alih memadamkan api, elite politik secara arogan menyebut “anggota DPR tak bisa disamakan dengan rakyat jelata”. Atau, menuduh “mental orang tertolol sedunia”. Bagi Gen Z, kalimat ini adalah bensin yang justru membesarkan api kemarahan.
Mereka membedah masalah secara pragmatis, menuntut transparansi, dan menggunakan kreativitas sebagai senjata utama. Aksi-aksi mereka, baik online maupun di jalanan, adalah cerminan dari keinginan yang mendalam akan akuntabilitas dan keadilan sosial.
Pada “revolusi Gen Z” 2025 ini, kita bisa melihat dengan jelas dari Indonesia hingga Nepal bahwa Gen Z adalah kekuatan politik di masa kini. Mereka telah mendefinisikan ulang makna partisipasi, menjembatani dunia digital dan fisik, dan membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari layar HP yang kita genggam. Kekuasaan telah berpindah tangan, dan kini berada dalam genggaman generasi yang siap untuk menuliskan sejarahnya kembali. (*)