Kecimol; antara Estetika dan Etika
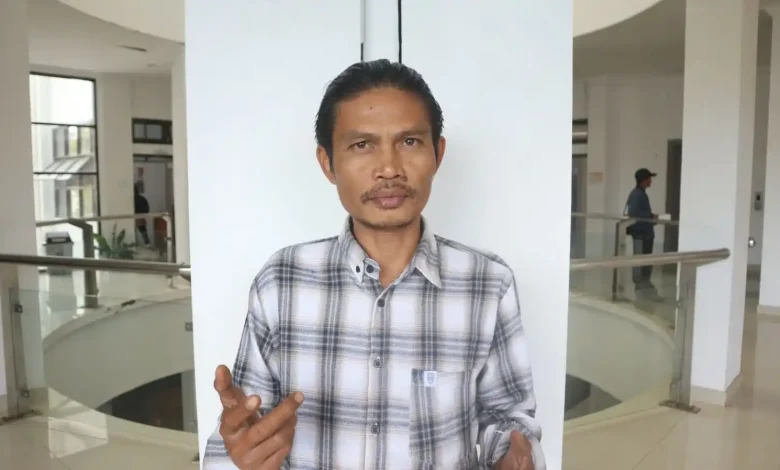
Oleh: Harianto – Jurnalis lepas dan peneliti budaya di Lombok Research Center (LRC)
Akhir pekan di sepanjang jalan-jalan kabupaten hingga sudut desa-desa di Pulau Lombok, dentuman musik dan gerak tubuh para penari kecimol kian sering menghiasi perayaan nyongkolan—arak-arakan pengantin dalam tradisi lokal.
Gendang bertalu-talu, seruling melengking, suara organ tunggal menggema dari mobil pikap yang dimodifikasi. Di belakangnya, para pemuda dan pemudi menari, tubuh bergoyang mengikuti irama yang riang dan memabukkan. Sebagian menyebutnya sebagai hiburan rakyat yang ekspresif. Sebagian yang lain mengernyitkan dahi: ini sudah kelewatan.
Saya berdiri di antara dua kutub itu. Sebagai orang yang pernah mencicipi dunia seni pertunjukan, saya tahu betapa panggung bisa menjadi medium perayaan dan perlawanan sekaligus.
Namun sebagai bagian dari masyarakat, saya juga menyadari pentingnya rambu. Di situlah tarik-ulur antara estetika dan etika dalam seni berlangsung: kadang senyap, kadang gaduh, tapi selalu relevan untuk dibicarakan.
Kecimol, dalam bentuk asalnya, tak lebih dari sebuah orkes jalanan. Ia merupakan bagian dari ekosistem budaya pop lokal yang tumbuh dari akar masyarakat.
Kecimol lahir bukan di ruang konser ber-AC, tapi di jalan-jalan kampung, di tengah pesta kawinan rakyat jelata, yang ingin pernikahan anaknya dirayakan dengan meriah. Kecimol bukan pentas eksklusif untuk bangsawan, melainkan wajah kesenian rakyat yang egaliter, spontan, dan berani.
Persoalan muncul ketika pertunjukan ini dianggap—atau berubah menjadi—aksi yang mempertontonkan erotisme. Penari perempuan bergoyang di atas mobil dengan gerakan tubuh yang mengundang.
Penonton laki-laki bersorak, tak jarang ada yang naik ke panggung dadakan itu, ikut menari, kadang kehilangan kendali. Estetika kecimol yang semestinya membangkitkan rasa gembira, justru berubah menjadi polemik yang mengundang pelarangan di berbagai tempat.
Bukan tanpa alasan kecimol jadi sorotan. Di banyak kasus, yang ditonjolkan bukan lagi musik atau lagu yang dibawakan, melainkan tarian penarinya yang dianggap vulgar. Maka tak mengherankan jika sebagian masyarakat mulai bertanya, ke mana arah kesenian rakyat kita?
Kecimol yang Dulce et Utile
Saya teringat kembali pada pelajaran dasar dalam seni bahwa segala bentuk ekspresi artistik, sekecil apa pun, seharusnya membawa dua nilai utama. Dulce et utile—manis atau indah dan berguna.
Ini dikemukakan oleh Horatius, penyair dan filsuf Romawi. Dulce bermakna menyenangkan, indah, menghibur; sementara utile berarti mengandung manfaat, menyentuh akal sehat dan rasa moral penontonnya.
Sayangnya, di era media sosial yang serba viral dan instan ini, nilai ‘dulce’ kerap dimaknai secara sempit. Yang penting menghibur, ramai, dan seronok. Soal ‘utile’ belakangan. Seni dipandang sebagai pelarian, bukan pengayaan batin. Ia diekstrak jadi tontonan, kehilangan tuntunan.
Tapi kita tidak bisa menuding masyarakat begitu saja. Sebab dalam banyak hal, kecimol bisa juga dibaca sebagai semacam pemberontakan kultural—sebuah ekspresi atas kekangan sosial yang tak memberikan ruang bebas bagi kreativitas rakyat kecil.
Sama seperti dangdut jalanan di Pantura yang dulu juga dianggap musik “kelas bawah”, kecimol menyuarakan perayaan di tengah keterbatasan. Ini bukan semata-mata hiburan, tapi bentuk kepemilikan bahwa rakyat punya hak untuk bersuka cita dengan cara mereka sendiri.
Di sinilah peran etika menjadi penting. Etika bukan sekadar larangan, tapi kesadaran. Ia hadir untuk menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan kepantasan bersama.
Dalam konteks kecimol, yang dibutuhkan bukan pelarangan total, melainkan penataan ulang panggung. Bukan pembungkaman, tapi penegasan ulang nilai.
Kita lupa, bahwa di Lombok sendiri ada banyak bentuk seni pertunjukan yang memikat sekaligus santun. Ada gendang beleq yang penuh semangat dan wibawa. Ada zikir zaman yang mistik sekaligus musikal. Bahkan kecimol, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi warna baru dalam seni pertunjukan yang enerjik, segar, dan edukatif. Tapi tentu dengan tetap mengakar pada norma sosial yang dijunjung bersama.
Saya membayangkan sebuah versi kecimol yang lebih estetis. Yang menampilkan kekuatan musikalnya, kekompakan gerak dan kostum, kekayaan lirik berbahasa Sasak atau Indonesia yang mengangkat tema cinta, kerja keras, atau kritik sosial. Bukan hanya tarian erotis yang menjadi pusat perhatian, tapi narasi budaya yang diusung melalui lagu dan koreografi yang terkonsep. Bukankah itu akan lebih membanggakan?
Tentu, perubahan seperti itu tidak bisa instan. Harus ada proses bersama. Masyarakat perlu diberi ruang untuk berdialog, bukan diintimidasi. Para pelaku seni harus diajak duduk bersama, bukan dituding sebagai biang kerok dekadensi. Pemerintah daerah dan tokoh adat bisa menjadi jembatan, bukan hanya pengawas.
Penataan Ulang Kecimol
Mungkin jalan tengah bisa dimulai dari sini: membuat aturan sederhana bagi setiap pertunjukan kecimol. Misalnya, membatasi usia penonton, durasi acara, jenis tarian, dan pakaian penari.
Lalu memberi pelatihan kepada para musisi dan penari kecimol tentang bagaimana menampilkan pertunjukan yang menarik namun tetap santun. Bahkan bisa dibuat lomba kecimol tahunan, sebagai bentuk apresiasi sekaligus pembinaan.
Banyak seniman di Lombok yang sebenarnya sangat terbuka terhadap gagasan pembaruan. Yang mereka butuhkan bukan larangan, tapi pemahaman. Bahwa seni bisa berkembang tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang tumbuh di tengah masyarakat.
Bagi saya pribadi, seni tidak hanya soal ekspresi, tapi juga cermin peradaban. Seni pertunjukan adalah wajah budaya kita. Jika ia disajikan secara sembarangan, maka yang tampak bukan hanya gerakan tubuh, melainkan arah kita sebagai masyarakat.
Kecimol adalah potret tentang bagaimana seni dan budaya pop lokal tumbuh, bertumbuk dengan zaman, dan kemudian diuji oleh norma. Ia adalah ruang tawar-menawar antara estetika dan etika. Dan sebagaimana hidup, seni pun perlu keseimbangan.
Maka, alih-alih mematikan kecimol, mengapa tidak kita bimbing ia menjadi lebih matang? Alih-alih menghapus panggungnya, mengapa tidak kita bantu memperluas cakrawalanya?
Sebab kecimol, jika diberi panggung yang tepat, bisa menjadi kekayaan baru dari Pulau Seribu Masjid ini. Bukan hanya di jalanan kampung, tapi juga di arena nasional, bahkan internasional. Tapi tentu, dengan wajah yang lebih beradab, lebih membumi, lebih membanggakan.
Sore itu, saat perjalanan pulang dari Lombok Timur menuju Kota Mataram, saya menyaksikan lagi iring-iringan nyongkolan melintasi dusun-dusun dan keluar ke arah jalan beraspal. Suara musik kecimol menggema.
Saya melihat anak-anak kecil menari mengikuti irama. Ibu-ibu tertawa. Para pemuda berjoget. Tak ada yang berlebihan. Tak ada yang menyimpang. Semuanya gembira dalam batas wajar.
Lalu saya membatin, mungkin inilah kecimol yang kita butuhkan, yang bisa merayakan kehidupan tanpa menginjak etika. Yang bisa menghibur tanpa menciderai rasa. Yang bisa menjadi dulce sekaligus utile—indah dan berguna.
Pada akhirnya, seni yang baik bukan hanya yang menggetarkan tubuh, tapi yang menggetarkan hati. Bukankah begitu esensi dari semua pertunjukan?. (*)






