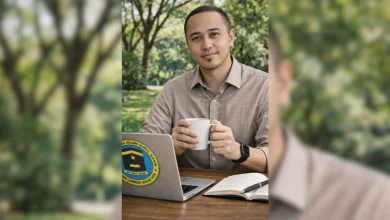Oleh: Harianto – Peneliti di Lombok Research Center (LRC)
Di sudut Selatan Pulau Lombok, ketika matahari belum sepenuhnya bangkit dan bau garam masih pekat di udara, sebuah ritus tua kembali menghidupkan ingatan: laut harus diistirahatkan. Tiga hari tiga malam, tak satu pun sampan nelayan diizinkan memecah ombak. Tidak ada jaring yang dilempar. Tak ada umpan yang dijatuhkan. Laut berpuasa. Manusia menepi. Semesta diajak tenang barang sejenak.
Nama ritualnya Nyelamaq di Lauq. Sebuah upacara adat yang tetap tegak berdiri di Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Saban tahun, para nelayan—utamanya dari klan Bajau, Bugis, dan Mandar—bersepakat menggelar prosesi syukur dan tolak bala dengan melarung kepala kerbau ke tengah laut. Ritual ini bukan hanya janji spiritual, tetapi juga wujud paling arif dari kearifan ekologis: menjaga laut agar tetap hidup, agar ikan tak punah, agar manusia tak serakah.
Saya mendengar kisah ini dari Abdul Hamid, nelayan sekaligus tetua adat Bajau berusia 56 tahun. Rumahnya menghadap langsung ke lautan. Ketika saya berkunjung akhir April lalu, ia menyambut saya dengan secangkir kopi dan cerita yang mengalir tenang seperti laguna saat pasang surut.
“Kami ini terbentuk dari kerasnya karang dan derasnya gelombang,” katanya sambil menyalakan rokok linting. “Kami tidak takut hujan atau angin. Jika musim ikan datang, kami tetap berlayar meski malam belum tuntas. Dan kami pulang saat mentari baru menyingsing, membawa rejeki dari perut laut.”
Perbincangan kami tak semata membahas ritual, tapi juga menyentuh pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana sebuah komunitas maritim seperti Tanjung Luar menjaga ketahanan pangan di tengah himpitan krisis iklim, kebijakan tambal sulam, dan invasi perahu-perahu besar dari luar? Jawabannya: dengan menyandarkan hidup pada laut, tanpa pernah benar-benar menaklukkannya.
Pekan berikutnya, saya mencoba menghubungi kembali Abdul Hamid. Ada diskusi kelompok terpumpun yang digelar oleh Lombok Research Center—tentang penguatan desa mandiri pangan di Lombok Timur. Tapi nomor ponselnya tak aktif. Saya lalu menghubungi Sekdes Tanjung Luar, Ari Arfansyah.
“Mohon maaf, kami ndak bisa hadir,” ujarnya di ujung telepon. “Pekan ini kami sibuk persiapan gawe adat Nyelamaq di Lauq. Tapi kami sudah utus warga lain.” katanya. Laut, tampaknya, selalu lebih duluan dipilih ketimbang forum diskusi. Dan barangkali memang begitu mestinya: apa arti forum tanpa laut yang tetap menyediakan makan?
Ritual Nyelamaq di Lauq dimulai dari kampung. Seekor kerbau diarak keliling selama tiga hari penuh. Sebuah peringatan dini bahwa laut sedang dalam masa penebusan. Setelah itu, kerbau disembelih, dan kepalanya—dihiasi benang emas dan doa-doa tua—dilarung ke tengah laut. Diiringi ratusan sampan dan denting musik sarone, kepala kerbau ditenggelamkan di sebuah terumbu karang berbentuk cincin, sejauh 1 hingga 3 mil dari daratan.
Namun tak sesederhana itu. Sebelum kepala kerbau dilempar ke laut, seorang sandro—dukun adat—mendapatkan bisikan, wahyu, atau intuisi tentang titik pelarungan. Karena laut, bagi orang Bajau, bukan sekadar hamparan air asin. Ia punya arah, punya isi, punya kehendak. Dan manusia mesti tahu diri.
Banyak versi tentang dari mana orang Bajau berasal. Ada yang menyebut mereka datang dari Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Ada yang melacak jejaknya dari Semenanjung Malaka. Ada pula yang percaya bahwa akar mereka tumbuh dari pesisir Sulawesi Selatan. Tapi di mana pun tempat asalnya, satu hal yang tak bisa dipungkiri: mereka adalah bangsa laut. Sea gypsies. Nomaden yang menjadikan gelombang sebagai rumah, bintang sebagai kompas, dan sampan sebagai warisan.
Di tengah godaan modernitas—dari alat tangkap canggih hingga kapal cantrang bersubsidi—komunitas nelayan Tanjung Luar tetap setia pada siklusnya sendiri. Mereka memaknai laut dengan irama, bukan logika eksploitasi. Bagi mereka, laut bukan untuk dikeruk, tapi untuk diajak berdialog. Dengan ritual. Dengan jeda. Dengan larangan.
Ketahanan pangan, dalam bahasa birokrasi, adalah soal angka: berapa ton produksi, berapa persen stunting, seberapa banyak bantuan sembako. Tapi di kampung pesisir seperti Tanjung Luar, ketahanan pangan adalah soal keberlangsungan: apakah besok masih ada ikan di laut? Apakah anak-anak nelayan masih bisa makan nasi dengan lauk? Apakah laut masih bisa dimintai maaf?
Pemerintah memang telah menelurkan regulasi: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, juga PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ada konsep Desa Mandiri Pangan yang digembar-gemborkan. Tapi apakah konsep itu mengenal istilah Nyelamaq di Lauq? Apakah ia paham bahwa kedaulatan pangan tak hanya dibangun dengan peta dan anggaran, tapi juga dengan menghargai ritual?
Kabupaten Lombok Timur adalah potret kecil dari wajah Indonesia yang sesungguhnya: agraris sekaligus maritim. Kaya sumber daya, namun seringkali miskin skema. Pembangunan kerap abai pada irama lokal, dan tak jarang menggusur kearifan yang telah tumbuh sebelum negara ini hadir.
Jika sempat hadir nanti di hari pelarungan, yang pada tahun ini akan digelar pada tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2025. Acara ritual adat ini akan dimulai dari tanggal 9 Juli 2025, di Tanjung Luar kita akan dapat menyaksikan ratusan sampan menari di atas arus gelombang.
Suara sarone berpadu dengan ombak. Wajah-wajah nelayan tampak khusyuk. Kepala kerbau akhirnya dilepas ke laut, seperti melarung beban hidup, harapan, dan rasa syukur sekaligus. Sejenak, laut menjadi altar. Manusia menjadi peziarah dan semesta menunduk.
Tiga hari tiga malam kemudian, laut akan kembali ramai. Sampan-sampan kembali berlayar. Ikan-ikan mungkin sudah lebih banyak. Tapi lebih dari itu, manusia dan laut telah berdamai, sekali lagi. Dan bukankah itu inti dari ketahanan pangan? Bukan hanya cukup makan, tapi cukup arif untuk mengetahui kapan waktunya harus berhenti. (*)