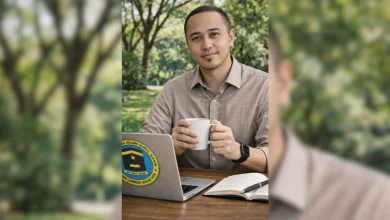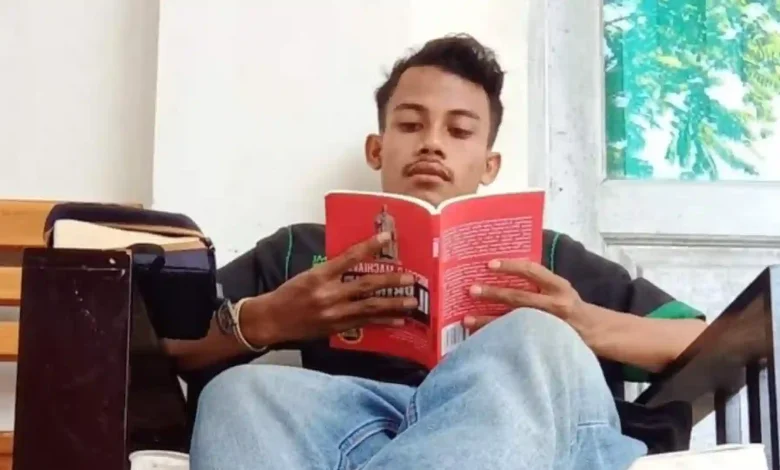
Oleh: Muhsinin – Mahasiswa Mataram
Delapan dekade sudah Indonesia mengibarkan benderanya di bawah langit merdeka. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa ini menempuh jalan panjang penuh harapan, darah, air mata, dan cita-cita luhur untuk membangun republik yang adil, makmur, dan berdaulat.
Namun, ketika kalender menandai usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul, apakah kemerdekaan ini benar-benar membebaskan bangsa dari belenggu penindasan, ataukah kita hanya berpindah dari satu bentuk kekuasaan ke bentuk yang lain yang lebih halus, tetapi tetap membelenggu?.
Kemerdekaan tidak hanya berarti memutus rantai kolonialisme fisik, ia juga menuntut pembongkaran sistem kekuasaan yang mengatur pikiran, membentuk kesadaran, dan menanamkan kepatuhan.
Antonio Gramsci pernah menegaskan bahwa hegemoni adalah dominasi yang dibangun, bukan semata-mata dengan kekerasan, melainkan juga dengan konsensus yang membuat penindasan tampak sebagai pilihan sukarela. Pernyataan ini mencerminkan realitas Indonesia hari ini, kita hidup dalam lanskap kekuasaan yang dibungkus dengan narasi demokrasi, kemajuan, dan pembangunan, tetapi tetap mengatur kehidupan rakyat melalui jaringan kepentingan politik-ekonomi yang sulit dicapai.
Jejak masa lalu kita masih terbayang, Orde Baru menjadi laboratorium besar penerapan hegemoni di Indonesia, di mana kekuasaan bertahan bukan semata karena kekuatan senjata, melainkan karena keberhasilan membentuk narasi tunggal pembangunan sebagai tujuan tertinggi bangsa.
Selama lebih dari tiga dekade, media dibungkam, pendidikan diarahkan untuk mencetak warga negara yang patuh, partai politik dikebiri, dan gerakan rakyat dibatasi. Hegemoni Orde Baru begitu efektif karena membuat rakyat menerima pembatasan kebebasan sebagai harga yang wajar demi stabilitas dan kemajuan.
Ketika Reformasi 1998 menggulingkan rezim Soeharto, harapan bahwa struktur hegemoni akan runtuh mencuat. Namun, kenyataannya ia hanya berganti rupa. Otoritarianisme lama bertransformasi menjadi demokrasi prosedural yang dikuasai oligarki, di mana partai politik tumbuh bebas, tetapi kerap menjadi alat transaksi kekuasaan dan ekonomi. Perubahan ini tidak memutus hubungan antara politik dan modal, justru memperkuatnya.
Demokrasi yang diidealkan sebagai ruang rakyat untuk menentukan arah bangsa kini berada dalam bayang kapitalisme oligarkis, di mana keputusan strategis lebih sering lahir di ruang rapat para pemilik modal daripada di forum rakyat.
Undang-undang yang dilahirkan tidak jarang mengamankan kepentingan korporasi besar dengan balutan narasi keberpihakan pada rakyat. UU Cipta Kerja, kebijakan hilirisasi, atau proyek infrastruktur berskala raksasa kerap dipoles sebagai bukti kemajuan, namun dalam praktiknya seringkali hanya menguntungkan segelintir elite, sementara rakyat kecil menjadi buruh murah atau sekadar penonton dalam panggung pembangunan.
Ruang publik digital seakan memberikan peluang baru untuk demokrasi yang lebih hidup, namun algoritma media sosial justru menciptakan medan yang dikendalikan oleh sumber daya finansial dan strategi komunikasi elite. Isu-isu penting seringkali tenggelam oleh perbincangan superfisial yang sengaja dipopulerkan.
Influencer yang di undang mempromosikan program pemerintah lebih sering berperan sebagai agen legitimasi, bukan kontrol sosial. Bahkan oposisi politik pun kerap masuk dalam permainan wacana yang diatur, di mana kritik menjadi komoditas untuk tawar-menawar kekuasaan, bukan jalan untuk perubahan mendasar.
Dalam arus politik yang demikian, kebudayaan masih menyimpan warisan feodalisme yang sulit dicabut. Relasi patron-klien tetap menjadi norma dalam birokrasi, politik, dan bahkan kehidupan sehari-hari. Pengagungan figur pemimpin, budaya asal bapak senang, hingga glorifikasi kemewahan pejabat telah menjadi tontonan rutin yang membius kesadaran rakyat.
Hegemoni masa kini tidak hanya hidup dalam aturan hukum atau kebijakan negara, melainkan juga merasuk melalui budaya populer. Film, musik, dan acara reality show kerap mengangkat narasi kesuksesan individual sebagai cita-cita tertinggi, seolah kemiskinan hanyalah akibat kurang kerja keras, bukan buah dari ketimpangan struktural. Nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong yang dulu menjadi identitas nasional, perlahan tersisih oleh logika kompetisi pasar.
Di tengah kondisi ini perlawanan terhadap hegemoni hanya mungkin dilakukan melalui lahirnya wacana tandingan yang konsisten dan terorganisasi.
Gramsci mengingatkan bahwa hal ini membutuhkan peran intelektual organik, mereka yang berpihak pada rakyat dan membangun narasi alternatif dari bawah. Sayangnya, banyak gerakan rakyat dan organisasi masyarakat sipil justru tersandera oleh pendanaan, kooptasi politik, atau logika media yang mengutamakan sensasi ketimbang substansi.
Tanpa upaya sistematis untuk membangun kesadaran kritis, perayaan kemerdekaan akan terus menjadi seremonial tanpa makna, sementara struktur yang menindas tetap bertahan dengan wajah baru.
Menjadi merdeka sejati berarti berani menggugat hal-hal yang selama ini dianggap wajar, mengapa pembangunan selalu diukur dari beton dan aspal, bukan dari keadilan sosial? Mengapa demokrasi diartikan sebatas pemilu lima tahunan, bukan partisipasi aktif rakyat setiap hari? Mengapa nasionalisme direduksi menjadi slogan dan atribut, sementara kebijakan ekonomi membuka pintu lebar bagi dominasi modal asing? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar kritik, tetapi kompas moral untuk mengarahkan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan yang substansial.
Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, serta ketimpangan ekonomi yang kian menganga, menunjukkan bahwa sistem lama tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman.
Persoalannya, apakah sistem baru yang kelak lahir akan benar-benar membebaskan atau sekadar reinkarnasi hegemoni lama dalam kemasan modern? Jika kemerdekaan hanya berarti pergantian wajah kekuasaan tanpa pembongkaran struktur yang menindas, maka 80 tahun kemerdekaan Indonesia hanyalah angka tanpa makna.
Tugas generasi kini adalah memastikan kemerdekaan tidak berhenti pada simbol, melainkan menjadi kenyataan yang dirasakan di meja makan rakyat, di ladang petani, di ruang kelas sekolah, dan di hati nurani bangsa.
Merdeka belum selesai jika petani masih kalah melawan korporasi, buruh bergaji rendah, rakyat kecil membayar mahal untuk pendidikan dan kesehatan, serta ruang publik dikuasai segelintir pemilik modal. Kita tidak bisa terus membungkus diri dengan nostalgia perjuangan sambil mengabaikan misi yang belum tuntas.
Merdeka bukan hanya soal mengusir penjajah di masa lalu, tetapi juga membebaskan diri dari belenggu struktural yang menindas.
Jika bangsa ini terus menelan bulat-bulat narasi yang disajikan oleh kekuasaan, perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia kelak mungkin akan berlangsung dalam kondisi yang sama: merdeka di atas kertas, terjajah dalam pikiran, hati, dan kehidupan sehari-hari.
Maka, tugas hari ini bukan sekadar mengenang, melainkan memutus rantai—rantai kebodohan yang diwariskan, rantai ketundukan yang dipelihara, dan rantai kekuasaan yang berganti tangan tanpa berganti watak. Tanpa keberanian itu, kemerdekaan hanya akan menjadi pesta tanpa ruh, sementara bangsa ini perlahan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. (*)