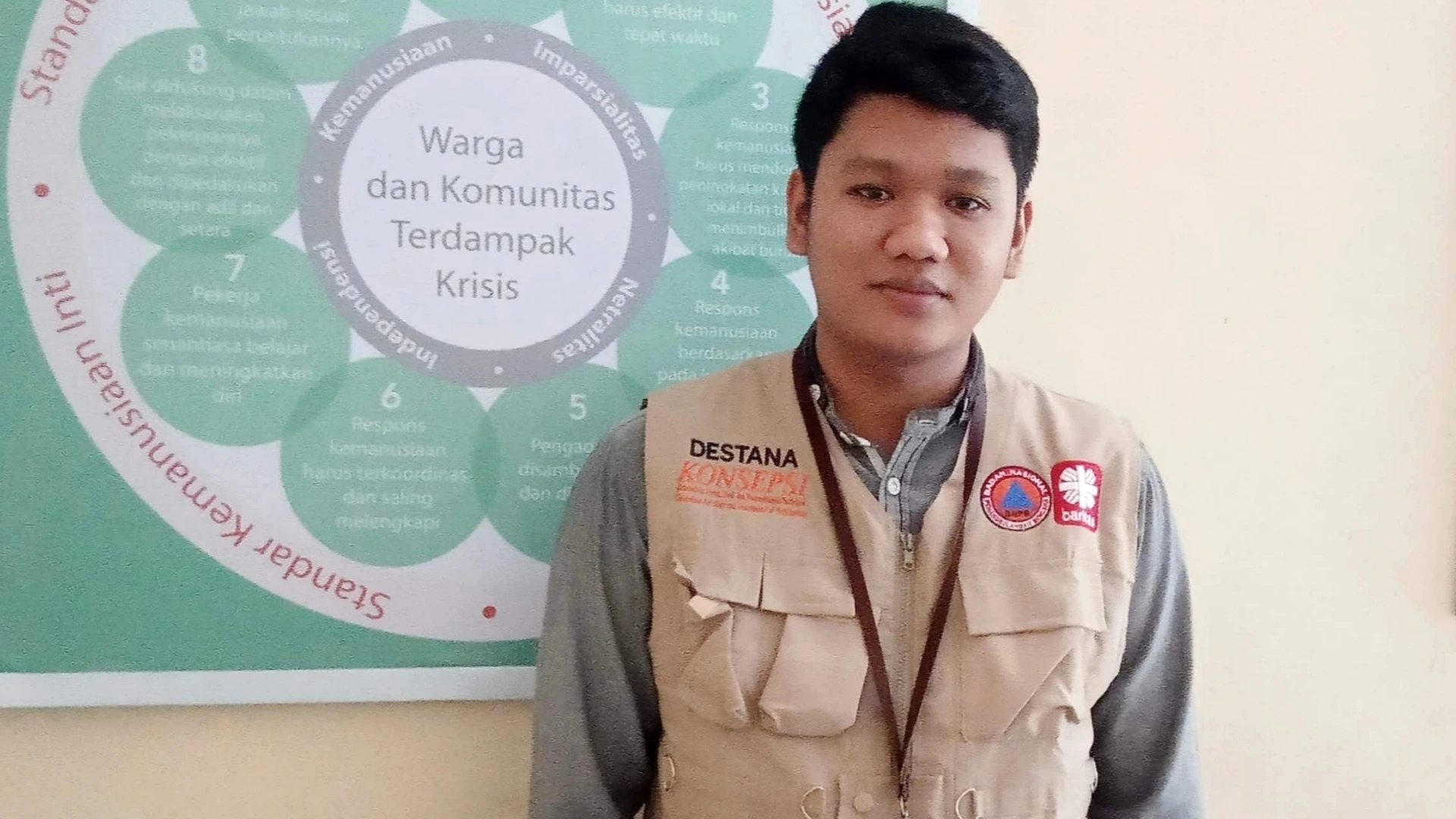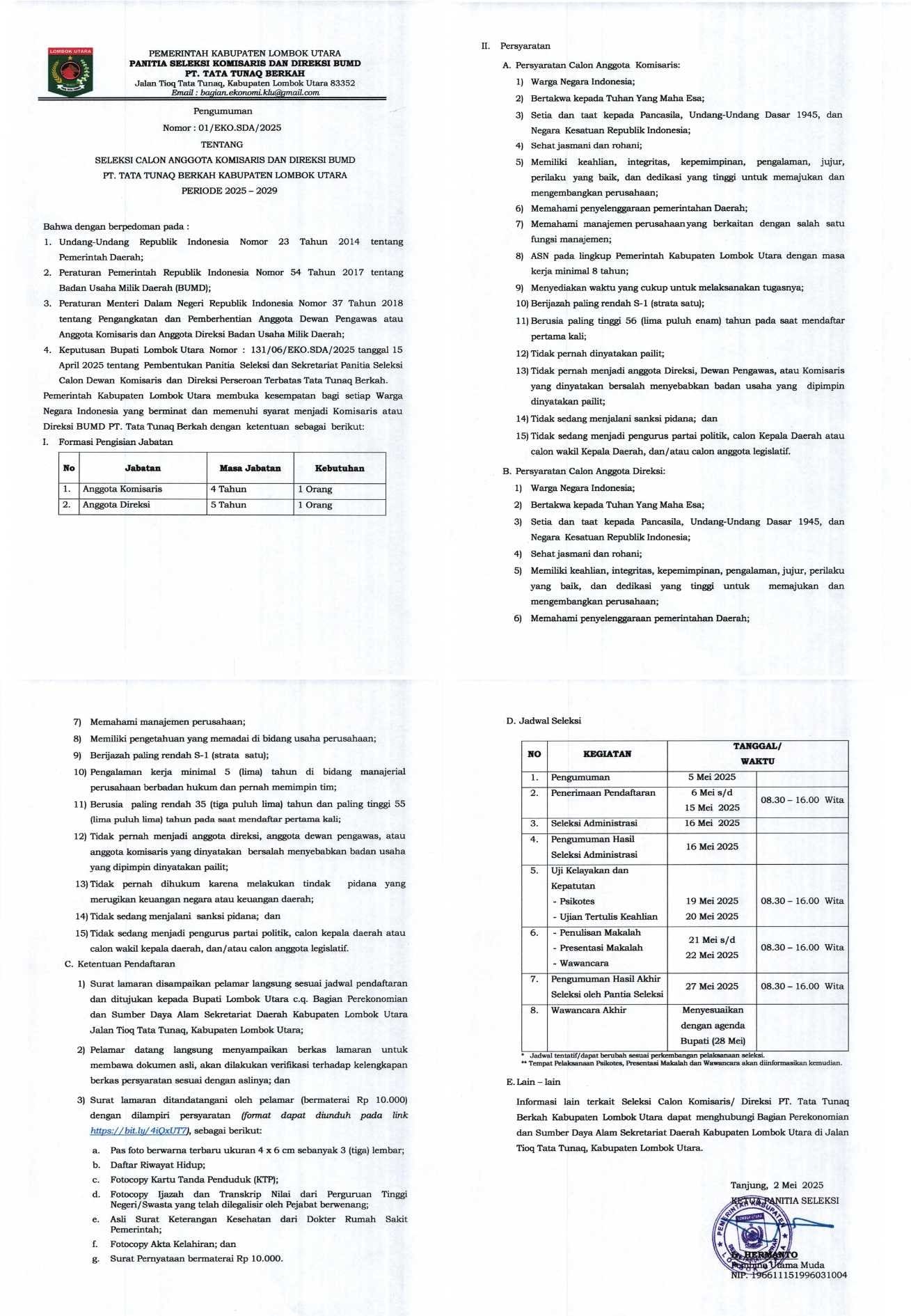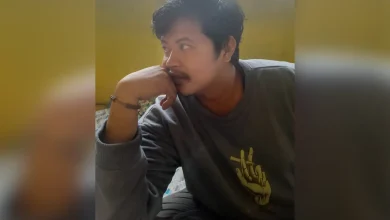Oleh: Hendra P. Saputra – Pegiat Kebencanaan KONSEPSI NTB
“Penyandang disabilitas bukanlah orang cacat. Sebab istilah cacat lebih tepat disematkan untuk benda, bukan kepada orang”. Ucapan itu disampaikan oleh Sri Sukarni, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB, saat saya mewawancarainya dalam rangka penelitian tesis tahun 2024 yang lalu. Dari ucapan itu, saya bisa memahami betapa kuatnya stigma sosial yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas. Mereka kerap kali dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak berdaya dan dianggap tidak memiliki kapasitas. Pandangan yang keliru ini sering kali tercermin dalam sistem penanggulangan bencana kita, di mana kebutuhan dan keberadaan penyandang disabilitas masih jarang mendapat perhatian yang serius.
Kerentanan Disabilitas dalam Bencana
Bagi sebagian orang, sirene peringatan dini adalah panggilan untuk segera menyelamatkan diri. Tapi bagi seorang tuna rungu, suara itu mungkin tidak terdengar. Bagi sebagian warga, instruksi evakuasi dapat dibaca dan dipahami dengan cepat. Tapi bagi seorang tuna netra, informasi itu bisa menjadi hal yang membingungkan. Ketika tangga darurat menjadi satu-satunya akses keluar dari gedung yang mulai runtuh karena gempa, bagaimana dengan mereka yang menggunakan kursi roda?
Maka dari itu, ketika bencana datang, penyandang disabilitas kerap kali “terlewat” dari lensa perhatian dalam setiap siklus kejadian bencana. Padahal kejadian bencana tidak pernah memandang usia, gender, dan status sosial. Tapi kenyataannya, kejadian bencana justru selalu menyisakan derita kemanusiaan yang lebih dalam bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Data United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki risiko empat kali lebih tinggi ketika terjadi bencana jika dibandingkan kelompok masyarakat pada umumnya.
Sejumlah studi telah mengkonfirmasi bahwa pengalaman bencana di masa lalu memperlihatkan penyandang disabilitas hampir selalu berada di posisi paling tertinggal. Misalnya, peristiwa tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, gempa Lombok, hingga bencana non-alam pandemi Covid-19, semua memperlihatkan pola yang sama: mereka terlambat mengakses informasi, tidak mengetahui jalur evakuasi, jauh dari jangkauan bantuan kemanusiaan, bahkan berisiko tinggi menjadi korban jiwa dan luka-luka.
Secara sosiologis, tingginya kerentanan yang dimiliki penyandang disabilitas ini bukan semata-mata persoalan akses fisik, tetapi karena ketimpangan struktur sosial yang menempatkan mereka dalam posisi marginal bahkan sebelum bencana terjadi. Mereka mengalami eksklusi sosial yang berlapis-lapis mulai dari kemiskinan, stigmatisasi, diskriminasi, dan hambatan struktural yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi dalam membangun kesiapsiagaan bencana.
Padahal dari sisi regulasi, pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas sudah cukup jelas. Indonesia telah mengadopsi prinsip inklusi ke dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 dan mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara normatif, negara mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan dilibatkan dalam pengurangan risiko bencana. Namun, di tingkat implementasi sayangnya masih belum dilaksanakan secara bermakna. Misalnya, banyak daerah belum memiliki data terpilah mengenai penyandang disabilitas. Kalau pun ada, sering kali data yang tersedia tidak update dan tumpang tindih. Padahal, data adalah dasar dari setiap perencanaan program untuk membangun ketangguhan yang inklusif terhadap bencana. Karena itu, data tidak hanya sekedar angka dan angka tidak hanya sekedar data. Tetapi di balik data, ada nilai dan kepentingan publik yang harus diperjuangkan (Pitaloka, 2023).
Masih lemahnya perspektif disabilitas dalam manajemen risiko bencana menunjukkan kesenjangan struktural dalam tata kelola kebencanaan kita. Rencana evakuasi jarang mempertimbangkan aksesibilitas. Informasi kebencanaan jarang disediakan dalam format ramah disabilitas, seperti bahasa isyarat, braille, atau infografik sederhana. Bahkan tempat pengungsian sering kali tidak dilengkapi dengan fasilitas dasar untuk penyandang disabilitas, seperti toilet khusus atau jalur landai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita masih terlalu mementingkan pendekatan umum dalam penanggulangan bencana. Kita sering menganggap bahwa satu prosedur evakuasi bisa berlaku untuk semua orang, padahal kenyataannya sangat berbeda. Kita butuh pendekatan yang inklusif, yang memahami keragaman kebutuhan warga dalam situasi krisis.
Hal itu penting karena data menunjukkan jumlah penyandang disabilitas bukan kelompok kecil. Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, tercatat ada 28,05 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, mayoritas tinggal di daerah-daerah rawan bencana. Namun dalam banyak rencana kontingensi, data mereka jarang dimasukkan dalam perhitungan, baik dari segi perencanaan evakuasi, pelatihan tanggap darurat, maupun distribusi bantuan.
Oleh karena itu, kisah tentang penyandang disabilitas dalam konteks kebencanaan sering kali adalah kisah tentang keterlambatan, keterbatasan, dan keterabaian. Maka, sudah saatnya kita perlu membangun sistem yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Pelatihan kebencanaan harus melibatkan penyandang disabilitas, bukan sekadar menjadikan mereka objek bantuan. Fasilitas umum harus dirancang agar dapat diakses semua orang. Hal yang paling penting juga adalah penyandang disabilitas harus dilibatkan sebagai subjek mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi program, bukan semata-mata sebagai objek yang tak berdaya.
Pembelajaran dari NTB
Harapan untuk menyemai ketangguhan inklusif sedang dilakukan oleh Provinsi NTB. Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB adalah wujud nyata dari komitmen untuk mendukung pengarusutamaan inklusi sosial dalam isu kebencanaan. Pembentukan ULD BPBD NTB menegaskan bahwa inklusi bukan persoalan belas kasihan, tapi soal keberpihakan pada keadilan. Semangat ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana harus dirancang untuk semua. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan lebih banyak nyawa, tetapi juga membangun masyarakat yang tangguh dan setara.
Secara kelembagaan, ULD BPBD NTB telah menjadi wadah strategis dalam mengarusutamakan suara penyandang disabilitas dalam isu kebencanaan. Kehadirannya memungkinkan advokasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pengurangan risiko bencana mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif kelompok rentan. Dengan mengedepankan partisipasi aktif, ULD membuka ruang dialog antara pemerintah dan komunitas disabilitas sehingga kesenjangan akses dan perlindungan dapat diatasi secara konkret.
Lebih dari sekadar lembaga, ULD BPBD NTB juga melahirkan focal point yang konsisten mengawal isu inklusi dalam pembangunan. Focal point ini memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan memastikan bahwa agenda inklusif menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, inklusi tidak hanya menjadi slogan, tetapi dijalankan sebagai prinsip dasar dalam mewujudkan masyarakat yang adil, tangguh, dan responsif terhadap kebutuhan semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Semoga. (*)